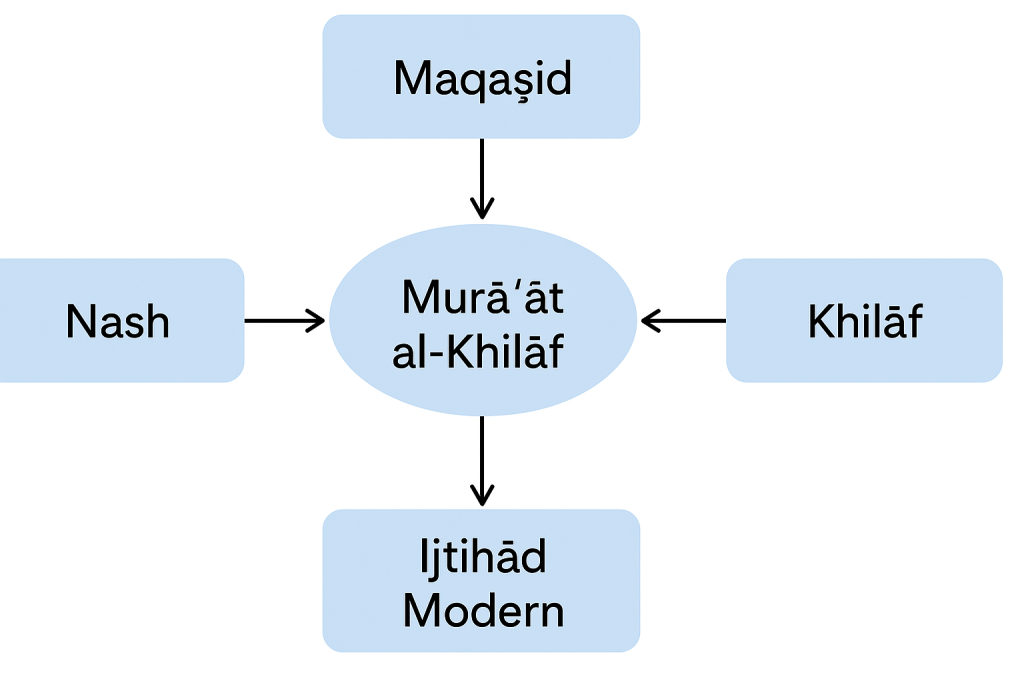(Kerudung dan Sanggul di Balik Konflik Identitas)
Bab 1: Undangan dan Keretakan
Angin sore yang gerah menyelinap melalui jendela studio kampus, tidak cukup untuk mendinginkan ruangan, apalagi pikiran Aisyah. Di depannya, selembar kain kasa putih terjuntai dari rangka kayu, seperti sebuah hantu yang tertangkap. Di lantai, berkutat dengan lem dan gunting, ia sedang menciptakan “Dinding yang Bernapas”, instalasi untuk pameran tugas akhirnya. Karya itu adalah protesnya yang sunyi terhadap segala sesuatu yang kaku, yang mengekang, yang dianggap final.
Tangan-tangannya yang lincah menempelkan potongan-potongan kain sutra tipis berwarna bumi ke jaring kasa, menciptakan lapisan transparan yang bergerak halus setiap kali ada hembusan angin. Kain-kain itu mewakili kulit, ingatan, sejarah yang tertumpuk namun tetap bisa ditembus. Di tengah konsentrasi yang nyaris sempurna itu, teleponnya bergetar di atas meja kayu yang penuh coretan sketsa. Sebuah pesan dari Bunda Arum, ibunya.
“Ais, besok Minggu kita ke rumah Mbah Rara ya. Ada undangan penting dari keluarga Pakde Heru. Bawa busana yang sopan.”
Aisyah menghela napas. “Undangan penting” dan “rumah Mbah Rara” adalah kombinasi yang selalu membuat jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Itu berarti dunia lain—dunia dengan tata krama yang rumit, dengan pandangan yang mengukur, dengan harapan-harapan yang berbobot seperti batu candi.
Esok harinya, aroma melati dan kayu jati tua menyambutnya di pendapa rumah keluarga besar. Rumah itu sendiri adalah sebuah pernyataan: kokoh, anggun, penuh dengan benda-benda yang seolah menyimpan bisik-bisik zaman. Di ruang tengah, duduklah Mbak Rara, neneknya. Di usianya yang keenam puluh lima, posturnya masih tegak bagai patung perunggu, rambutnya yang memutih disanggul rapi dengan konde cespleng, sederhana namun penuh wibawa. Matanya yang masih tajam langsung menyapu Aisyah dari ujung kepala hingga ujung kaki, berhenti sejenak di kerudung katun lembut warna krem yang dengan rapi menutupi rambut dan lehernya.
“Aisyah, kemari,” suara Mbak Rara lembut namun penuh otoritas.
Aisyah mendekat, mencium tangan neneknya. Bunda Arum sudah duduk di samping dengan ekspresi was-was yang coba ditutupi senyum.
“Ini,” ujar Mbak Rara, menggeser selembar undangan beraksen emas dan merah marun ke arah Aisyah. “Pernikahan Gendhis, putri Pakde Heru. Kau harus datang. Ini acara besar keluarga.”
Aisyah membuka undangan itu. Kalimat-kalimat dalam bahasa Jawa Krama dan Indonesia bercampur, penuh dengan gelar dan sapaan hormat. Di bagian bawah, tertulis jelas: “Diharapkan mengenakan busana adat Jawa lengkap.”
Jantungnya tercekat. ‘Busana adat Jawa lengkap’ adalah sebuah kode. Itu berarti kebaya, kain jarik yang dililit, dan… sanggul. Bukan sanggul sehari-hari, melainkan sanggul upacara yang rumit, yang menuntut rambut tersanggul rapi tanpa sehelai pun terlepas. Sebuah mahkota tradisional yang akan membuat kerudungnya—bagian dari dirinya selama enam tahun terakhir—mustahil untuk dikenakan.
“Aku… Bisa tidak memakai kebaya yang lebih sederhana, Mbah? Atau…” suara Aisyah hampir bergetar.
Mbak Rara menghela napas panjang, seperti seorang guru yang kecewa pada murid yang tidak kunjung paham. “Gendhis adalah putri pertama dari garis ningrat kita, Aisyah. Kehadiran kita adalah bentuk penghormatan. Dan penghormatan itu ditunjukkan dengan tata busana yang sepantasnya.” Matanya menatap kerudung Aisyah. “Kau sudah memilih jalanmu, itu hakmu. Tapi jangan lupa, darah yang mengalir dalam tubuhmu adalah darah yang sama yang telah menjaga tata krama dan keanggunan ini selama ratusan tahun. Di acara seperti ini, kita adalah bagian dari garis itu. Sanggul, nak, itu bukan sekadar hiasan rambut. Itu adalah mahkota seorang perempuan Jawa. Lambang kesiapan, kematangan, dan kehormatannya. Aku ingin sekali melihatmu memakainya.”
Kata-kata itu menghunjam seperti paku. “Mahkota.” Ia merasa kerudungnya yang lembut tiba-tiba terasa panas, seperti sebuah perisai kecil yang tak berdaya menghadapi meriam budaya yang begitu besar. Di matanya, sanggul adalah simbol dunia yang indah namun asing, sebuah penanda kelas dan tradisi yang ia kagumi dari jauh tetapi juga dirasanya membatasi. Kerudungnya adalah ruang pribadinya, keheningan spiritualnya, identitas yang ia pilih setelah bertahun-tahun bertanya.
“Tapi Mbah, aku… aku tidak nyaman jika tidak berkerudung,” bantahnya pelan, berusaha menjaga sikap sopan.
“Satu hari saja, Aisyah,” sela Bunda Arum dengan suara mendamaikan, mencoba menjembatani jurang antara ibunya dan anaknya. “Untuk menghormati keluarga.”
Mbak Rara mengangguk, matanya tak lepas dari Aisyah. “Persis. Menghormati. Terkadang, menghormati leluhur dan adat itu butuh pengorbanan kecil. Pengorbanan rasa ‘nyaman’ pribadi.” Ucapan ‘nyaman’ itu diberi penekanan halus.
Pengorbanan. Kata itu menggantung di udara yang sesak. Bagi Aisyah, melepas kerudung di tengah keramaian bukanlah pengorbanan kecil. Rasanya seperti menyuruhnya berbicara tanpa suara, hadir tanpa diri. Tapi tekanan dari sorot mata neneknya, dan harapan diam dari ibunya, terasa begitu berat.
“Aku… akan memikirkannya, Mbah,” jawab Aisyah akhirnya, menunduk. Itu adalah kata-kata untuk mengakhiri pembicaraan, untuk melarikan diri sejenak.
“Jangan terlalu lama berpikir,” ujar Mbak Rara sambil meminum tehnya. “Waktunya tidak banyak. Gendhis menikah bulan depan. Aku ingin kau hadir sebagai perempuan seutuhnya, bukan sebagai…” ia berhenti sebentar, mencari kata, “… sebagai bayangan yang bersembunyi.”
“Bersembunyi.” Kata itu seperti tamparan. Aisyah mengatupkan bibirnya, mencegah kata-kata penuh amarah yang sudah menggelinding di ujung lidah. Ia berpamitan dengan cepat, mendengar gemerisik kain kebaya Bunda Arum yang berusaha menenangkan Mbak Rara.
Perjalanan pulang ke kosnya sunyi. Pikirannya berisik. Bayangan sanggul rapi bergulat dengan sensasi kain kerudung yang ia usap-usap secara tak sadar. Ia teringat karya instalasinya, “Dinding yang Bernapas”. Kini, ia sendiri yang merasa seperti dinding itu—ditekan, ditarik, diharapkan bisa bergerak lentur namun dituntut untuk mempertahankan bentuk tertentu. Di tengah geliat budaya sanggul yang megah dan penuh tuntutan, kerudungnya terasa seperti benteng terakhir yang sangat personal, namun kini dikepung oleh pasukan tradisi yang dipimpin oleh orang yang paling ia cintai dan hormati.
Keretakan itu bukan lagi retakan halus di tembok. Ia mulai membelah jantungnya.
Bab 2: Jejak Sanggul dalam Memoriku
Malam itu, di kamar kosnya yang sempit, Aisyah tak bisa lepas dari cengkeraman percakapan di rumah Mbak Rara. Kata-kata “bersembunyi” dan “mahkota” bergaung bergantian di kepalanya. Ia membuka laci kecil di bawah tempat tidurnya, mengeluarkan album foto tua yang ia selamatkan dari rumah. Kuliit sampulnya sudah lusuh, mengingatkan pada aroma kamar Mbak Rara.
Dibukanya halaman pertama. Di sana, tersenyum polos seorang bayi dengan pipi tembam, digendong oleh seorang perempuan anggun dengan sanggul gelung tekuk yang sempurna. Itulah dirinya dan Mbak Rara. Matanya tertarik pada sanggul itu—rapi, kompleks, tampak seperti mahkota yang hidup dari anyaman rambut hitam legam. Di foto lain, Mbak Rara sedang membungkuk, tangan lembutnya menuntun tangan mungil Aisyah untuk menyentuh hiasan tusuk konde berukiran bunga melati. Ekspresi wajah neneknya penuh kesabaran dan kebanggaan. Saat itu, sanggul adalah sesuatu yang indah, magis, bagian dari sosok nenek yang ia kagumi.
Kenangan itu hidup kembali. Aisyah kecil, duduk di beranda rumah keluarga, menonton Mbak Rara berlatih Srimpi. Neneknya tidak mengenakan kebaya mewah, hanya kain jarik dan kemben sederhana, tapi sanggulnya selalu rapi. Setiap gerakan kepala yang anggun, setiap lirikan mata yang tajam, seolah dikuatkan oleh sanggul yang tak goyah. Sanggul adalah pusat gravitasi keanggunannya. Aisyah dulu pernah meminta dicoba disanggul. Mbak Rara tertawa riang, mengumpulkan rambutnya yang masih tipis dan pendek, mencoba membentuknya. Hasilnya berantakan, tapi Mbak Rara bilang, “Nanti, kalau rambutmu sudah panjang dan kuat seperti Mbah, akan Mbah buatkan sanggul yang paling cantik.” Janji itu terasa hangat, sebuah inisiasi ke dunia perempuan dewasa yang penuh misteri.
Lalu, halaman album berganti. Foto-foto masa SMP-nya. Rambutnya sudah panjang, diikat sederhana. Ekspresinya mulai penuh tanda tanya. Di masa-masa itulah keraguan mulai tumbuh. Ia melihat teman-temannya mulai berkerudung, dan ia pun bertanya-tanya. Bukan karena ikut-ikutan, tetapi karena ada kerinduan akan sesuatu yang lebih privat, lebih dalam. Ia ingat sore hari di perpustakaan sekolah, tanpa sengaja membaca puisi tentang ‘ruang sakral seorang perempuan’. Ia ingat perasaan tidak nyaman ketika tatapan lelaki terlalu lama menyapu tubuhnya. Kerudung muncul dalam pikirannya bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai kemungkinan—sebuah ruang bernapas di tengah dunia yang semakin gaduh.
Halaman terakhir yang ia simpan khusus adalah fotonya sendiri, di usia enam belas tahun. Rambutnya masih terurai, tapi di kepalanya sudah terikat kerudung syal sederhana berwarna biru dongker. Foto itu diambil di kamarnya sendiri, matanya berbinar campur gugup. Itulah hari pertama ia memutuskan untuk konsisten berkerudung ke sekolah. Perasaannya saat itu masih jelas: sebuah ketenangan aneh, seperti akhirnya menemukan pelindung yang ia butuhkan untuk berpikir, untuk bergerak, tanpa menjadi terlalu ‘terlihat’ dalam cara yang tidak ia inginkan. Kerudung itu menjadi batas personalnya, sebuah pernyataan diam tentang haknya atas tubuh dan ruangnya sendiri.
Keputusan itu tidak serta merta diterima. Ayahnya, yang lebih moderat, hanya mengangguk. Bunda Arum khawatir—bukan pada kerudungnya, tapi pada dunia yang mungkin memperlakukannya berbeda. “Kamu sudah siap dengan pandangan orang, Nak?” tanyanya. Dan yang paling berat adalah reaksi Mbak Rara. Neneknya diam panjang saat melihatnya. “Kau yakin ini yang kau mau?” tanyanya, suaranya datar. “Jangan sampai ini hanya jadi penghalang untuk mengenal siapa dirimu sebenarnya.” Saat itu, Aisyah merasa kata-kata Mbak Rara tidak adil. Kini, berbaring di atas kasur, ia mempertanyakan: apakah kerudung menjadi penghalang untuk mengenali separuh dirinya yang lain—darah Jawa ningrat yang mengalir deras?
Tiba-tiba, ia teringat percakapan dengan Bunda Arum beberapa bulan setelah ia berkerudung. Mereka berdua sedang menyiapkan kue lumpur di dapur.
“Dulu, Mbah Rara juga punya banyak aturan untuk Bunda,” kata Bunda Arum sambil mengaduk adonan, suaranya rendah. “Harus begini, harus begitu. Cara duduk, cara bicara, cara berjalan. Sanggul itu… bagi Mbah, itu puncaknya. Itu bukti bahwa seorang perempuan sudah terdidik dengan baik, sudah siap menjalankan perannya dalam tata masyarakat.”
“Tapi perannya harus selalu ditentukan oleh orang lain, ya, Bun?” tanya Aisyah kala itu.
Bunda Arum tersenyum getir. “Susah, Nak. Kadang kita mencintai tradisi, tapi juga ingin bernapas lega di dalamnya. Dulu Bunda menikah dengan ayahmu yang bukan dari kalangan ningrat seperti kita, itu sudah dianggap ‘pemberontakan’ kecil oleh keluarga. Tapi Bunda memilih jalan itu agar bisa bernapas lebih lepas. Mungkin… kerudungmu adalah jalanmu untuk bernapas.”
“Lalu kenapa Mbah tidak bisa mengerti?”
“Karena bagi Mbah, tradisi yang ia jaga itu sudah seperti napasnya sendiri. Melihat kita memilih napas yang berbeda, itu terasa seperti kita menolak sebagian dari dirinya. Ia merasa tanggung jawabnya sebagai penjaga garis keturunan dan adat istiadat sedang diabaikan.”
Percakapan itu kini terasa baru maknanya. Ini bukan sekadar masalah kain di kepala. Ini adalah tabrakan dua sistem nilai, dua cara ‘bernapas’, dua bentuk cinta dan pengabdian yang sama-sama kuat namun saling menuntut pengakuan.
Aisyah menutup album foto. Matanya tertuju pada cermin di depan tempat tidurnya. Ia melihat pantulan dirinya: seorang perempuan muda dengan kerudung krem, wajahnya menyiratkan kebingungan yang dalam. Di balik bayangannya sendiri, seolah-olah ia bisa melihat siluet Mbak Rara dengan sanggulnya yang sempurna, diam, menunggu.
Ia bangkit, mendekati kanvas besar yang bersandar di dinding, coretan awalnya untuk “Dinding yang Bernapas”. Ia mengambil arang, dan dengan gerakan impulsif, ia menggambar dua siluet di atas sketsa kain transparannya. Satu figur dengan kontur sanggul yang tegas dan kokoh. Satunya lagi dengan garis kerudung yang jatuh lembut mengikuti bahu. Kedua figur itu saling membelakangi, namun bayangan mereka di tanah, yang ia goreskan dengan garis-garis putus-putus, justru saling menyatu dan berkelindan.
Mungkin itulah dirinya. Dua entitas yang saling membelakangi dalam kesadarannya, namun akarnya, bayangannya, sejarahnya, sudah tak terpisahkan.
Lalu, pikirannya melayang pada janji Mbak Rara: “Akan Mbah buatkan sanggul yang paling cantik.” Janji masa kecil yang dulu terhangatkan, kini terasa seperti sebuah utang yang akan ditagih. Sebuah mahkota yang ditawarkan dengan cinta, namun terasa seperti beban.
Ia mematikan lampu, mencoba tidur. Dalam gelap, yang terlihat bukanlah kegelapan, tetapi dua bentuk yang terus-menerus bergulat: sanggul yang rapi dan anggun, serta kerudung yang lembut dan membungkus. Keduanya adalah bagian dari memorinya, keduanya adalah jejak yang dalam. Pertanyaannya sekarang, bisakah kedua jejak itu berjalan beriringan tanpa harus menghapus yang lain? Atau, seperti dalam foto-foto albumnya, satu harus menghilang agar yang lain bisa muncul?
Bab 3: Riset untuk Karya, Penggalan untuk Diri
Kampus seni di pagi hari selalu memancarkan energi kreatif yang liar. Suara ketukan palu, derit gergaji, dan aroma cat serta tanah liat bercampur menjadi semacam simfoni produktivitas. Tapi bagi Aisyah, hari ini simfoni itu terdengar seperti desahan pikiran yang tak karuan.
Rendra, dengan kaus oblong sobek di bagian lengan dan celana chino belel, sudah menunggu di depan perpustakaan kampus, bersandar di tembok dengan buku sketsa tertatih di pinggang. “Dari jauh sudah kelihatan awan mendung di atas kepala Aisyah,” sambutnya dengan senyum khas, sedikit sarkastik namun hangat.
“Jangan mulai, Ren,” gerutu Aisyah, memperbaiki kerudungnya yang sedikit tertiup angin. “Aku lagi punya masalah keluarga rumit.”
“Lebih rumit dari instalasi ‘Dinding Bernapas’ yang katanya harus bisa menangis itu?” tanya Rendra sambil mereka berjalan masuk ke dalam perpustakaan yang sejuk.
“Lebih personal. Lebih… di sini,” jawab Aisyah menepuk dadanya.
Mereka duduk di meja di sudut khusus koleksi budaya. Rendra mencari referensi tentang arsitektur tradisional untuk latar panggung teaternya. Aisyah, dengan niat ganda, mulai mencari buku-buku tentang tata busana Jawa, khususnya tata rias dan sanggul.
Saat Rendra tenggelam dalam buku tentang struktur pendapa, Aisyah membuka sebuah buku besar bergambar berjudul “Ragam Busana dan Tata Rias Pengantin Jawa”. Halaman demi halaman dipenuhi oleh foto-foto perempuan dengan sanggul yang megah, rumit, dan berbeda-beda. Sanggul bokor mengkurep, sanggul tekak, gelung bun, sanggul podang—setiap nama memiliki filosofi dan status sosialnya sendiri. Ia membaca dengan intens, menemukan bahwa sanggul bukan hanya soal kecantikan.
“Sanggul Podang, dengan konde yang tinggi menjulang, melambangkan kekuatan dan kewibawaan seorang putri.”
“Gelung Tekuk, yang lebih rendah dan rapat, menandakan kesederhanaan dan kesiapan melayani.”
“Hiasan bunga melati dan kanthil dalam sanggul melambangkan kesucian dan ikatan yang harum sepanjang masa.”
Setiap helai rambut yang disanggul ternyata punya cerita. Setiap lekukan punya makna. Ini adalah bahasa yang sama sekali asing baginya, bahasa yang selama ini ia dengar tetapi tak paham.
“Lagi riset buat pameran? Kok wajahmu kayak lagi baca manifesto revolusi?” bisik Rendra, menyadari ekspresi serius Aisyah.
“Aku… cuma mau paham,” jawab Aisyah pelan, jarinya menelusuri gambar detail sanggul bokor mengkurep. “Selama ini aku cuma lihat ini sebagai simbol tekanan. Tapi ternyata… ini adalah sebuah seni. Sebuah disiplin.”
Rendra mengintip bukunya. “Wah, berat. Ini kayaknya bukan cuma buat tugas akhir, ya?”
Aisyah menghela napas. “Pernikahan sepupu. Harus pakai ini.” Ia menunjuk gambar sanggul lengkap dengan hiasan emas.
Rendra bersiul pelan. “Dan itu bertentangan dengan prinsipmu?”
“Aku tidak tahu lagi apa prinsipku, Ren,” aku Aisyah, frustasi. “Aku pikir kerudungku adalah pilihanku. Tapi menolak ini terasa seperti menolak separuh diriku, separuh keluargaku. Menurutmu aku terlalu dramatis?”
Rendra memandangnya serius untuk sesaat, lalu menutup bukunya. “Aisyah, teater itu bukan cuma tentang dialog. Itu tentang konflik. Dan konflik paling menarik bukan antara hero dan villain, tapi di dalam diri sang hero sendiri. Kau sedang jadi pahlawan di drama hidupmu sendiri. Nikmati saja prosesnya.”
Kata-kata Rendra, meski ceplas-ceplos, ada benarnya. Ini adalah sebuah proses. Dan untuk memahaminya, ia butuh lebih dari buku.
Di catatan seorang dosen tamu, ia menemukan nama “Mbah Surti”, seorang pengrajin sanggul dan perias pengantin tradisional yang legendaris di wilayah Pasar Kliwon. Kabarnya, ia sudah berusia senja tetapi masih aktif. Tanpa pikir panjang, Aisyah memutuskan untuk mencarinya. Ini bukan lagi hanya untuk keluarga; ini untuk dirinya sendiri.
Rumah Mbah Surti ternyata bukan rumah besar. Sebuah rumah Jawa sederhana di gang sempit, tetapi terawat dengan baik. Terasnya dipenuhi dengan pot-pot berisi bunga melati dan kenanga. Aroma wangi itu menyambut Aisyah sebelum ia mengetuk pintu.
Seorang perempuan tua dengan tubuh ringkih dan wajah penuh kerutan, tetapi mata yang masih sangat jernih, membuka pintu. Rambutnya yang putih dan tipis disanggul kecil dengan rapi, dan—Aisyah memperhatikan—ia mengenakan kerudung tipis berwarna abu-abu yang menutupi sanggulnya, diikat sederhana di bawah dagu.
“Kulo nuwun, Mbah. Saya Aisyah. Mahasiswa seni. Boleh bertanya-tanya tentang sanggul?” sapa Aisyah dengan bahasa Jawa Krama yang terbata-bata.
Mbah Surti memandangnya sejenak, dari ujung kerudung kremnya hingga ke ujung jari. Senyum tipis mengembang di bibirnya yang keriput. “Tentu, anakku. Mari masuk.”
Di dalam ruang tamu yang sederhana, dipenuhi dengan foto-foto pengantin dari berbagai era dan puluhan konde, tusuk, serta hiasan rambut dari kuningan, perak, dan plastik dalam kotak kaca, Mbah Surti menyuguhkan teh hangat.
“Jadi, kenapa minat pada sanggul, nak? Biasanya anak muda sekarang lebih suka yang praktis,” tanya Mbah Surti.
Aisyah mengambil napas. “Saya… ada konflik, Mbah. Keluarga saya mengharuskan saya bersanggul untuk acara adat. Tapi saya,” ia menunjuk kerudungnya, “saya sudah memakai ini. Dan rasanya seperti harus memilih.”
Mbah Surti mengangguk pelan, seolah mendengar cerita yang tak asing. Tangannya yang berusia meraih sebuah sanggul bunting dari kayu yang sudah halus karena sering dipegang, bentuk dasar sanggul yang digunakan untuk praktik.
“Lihat ini,” katanya. “Ini hanya kayu. Tapi di tangan yang paham, ini bisa jadi tempat lahirnya keanggunan.” Ia meletakkannya. “Kau tahu, dulu saya juga seperti kamu. Dari keluarga santri, tapi cinta pada seni tata rias tradisional. Banyak yang bilang saya salah jalan.”
Aisyah terkejut. “Lalu bagaimana Mbah?”
“Saya belajar. Saya pahami. Saya hormati keduanya.” Mbah Surti menatapnya tajam. “Masalahmu, nak, bukan pada benda kain atau rambut yang disanggul. Masalahmu ada di sini,” ia menunjuk hati Aisyah. “Kau melihatnya sebagai pertarungan. Kerudung versus sanggul. Iman versus budaya.”
“Bukankah begitu, Mbah?”
Mbah Surti menggeleng, senyumnya bijak. “Benda itu punya rohnya sendiri, Nak. Tergantung niat hati yang memakainya. Sanggul ini,” ia tepuk-tepuk sanggul kayu, “bisa jadi simbol kesombongan jika dipakai untuk pamer. Bisa jadi simbol pengabdian jika dipakai dengan rendah hati untuk menghormati acara adat. Kerudungmu juga sama. Bisa jadi tameng untuk menghindar, atau bisa jadi mahkota kesadaran diri.”
Kata-kata itu menggema dalam diri Aisyah. Rohnya sendiri. Niat hati.
“Mbah masih memakai kerudung?” tanya Aisyah penasaran, melihat kerudung tipis yang melingkari leher Mbah Surti.
“Setiap hari,” jawabnya. “Tapi saat saya merias pengantin, saat saya menjadi bagian dari upacara adat yang sakral, saya fokus pada tugas saya. Saya menghormati roh dari acara itu, dari sanggul yang saya buat. Keyakinan saya di sini,” ia tepuk dadanya, “tidak lantas hilang karena saya membantu menghiasi kepala orang lain.”
Pelajaran itu sederhana namun sangat dalam. Selama ini Aisyah terjebak dalam dikotomi. Mbah Surti melihatnya sebagai lapisan yang bisa hidup berdampingan, selama niat dan pemahamannya jelas.
“Maksud Mbah, saya bisa menghormati tradisi tanpa harus mengkhianati keyakinan saya?”
“Bukan cuma menghormati, nak. Kau bisa memahami. Lalu, kau bisa memilih bagaimana caramu berpartisipasi.” Mbah Surti berdiri dengan sedikit terhuyung, mengambil sebuah tusuk konde sederhana dari kayu cendana. “Ini untukmu. Coba kau rawat dan pahami keduanya—warisan leluhurmu dan jalan spiritualmu. Mungkin jawabannya bukan memilih salah satu, tetapi… menemukan bahasamu sendiri.”
Aisyah menerima tusuk konde itu, terasa hangat dan ringan di tangannya. Bahasa sendiri. Itu seperti petunjuk yang samar, tetapi memberinya arah.
Perjalanan pulang dari rumah Mbah Surti terasa berbeda. Pikiran Aisyah tidak lagi penuh dengan pertarungan, tetapi dengan kemungkinan. Ia melihat perempuan tua dengan kerudung dan pengetahuan mendalam tentang sanggul. Ia melihat bahwa keduanya bisa hidup dalam satu orang, dengan damai.
Mobilnya berhenti di lampu merah. Di trotoar, ia melihat seorang perempuan muda dengan kebaya dan sanggul sederhana, sambil menatap layar ponsel. Di seberangnya, seorang perempuan dengan jilbab lebar sedang menjajakan gado-gado. Keduanya adalah potret perempuan Jawa masa kini, dengan ekspresinya masing-masing.
Mungkin, pikir Aisyah, ia tidak perlu menjadi salah satu dari mereka sepenuhnya. Mungkin ada ruang ketiga, sebuah ruang yang belum terpetakan, di mana ia bisa merangkai makna dari kedua dunia itu.
Sesampai di kos, ia tidak langsung membuka buku tugas. Ia duduk di depan cermin, memegang tusuk konde pemberian Mbah Surti. Dengan hati-hati, ia mencoba menyisir rambutnya, lalu mencoba membentuk sanggul sederhana di atas kepalanya. Tentu saja hasilnya berantakan, rambutnya terlalu pendek dan ia tidak punya keterampilan. Tapi ia tidak menyerah. Ia mengambil maneken kepala yang biasa ia gunakan untuk membuat instalasi topeng, dan mulai berlatih dengan potongan kain sebagai pengganti rambut.
Ia tidak sedang berlatih untuk pernikahan Gendhis. Ia sedang berlatih untuk memahami. Setiap gulungan kain yang ia bentuk, setiap tusukan konde yang ia coba, adalah bagian dari upayanya untuk mempelajari bahasa yang selama ini ia tolak. Untuk pertama kalinya sejak menerima undangan itu, ia merasa tidak terpojok. Ia merasa seperti seorang penjelajah yang baru saja menemukan peta tua, siap untuk memetakan wilayah dirinya yang belum dikenal.
Bab 4: Uji Coba yang Berantakan
Tekanan itu datang bukan lagi sebagai gelombang halus, melainkan sebagai batas waktu yang menggelantung di kalender. H-21 sebelum pernikahan Gendhis. Telepon dari Bunda Arum semakin sering, suaranya berusaha riang namun terbaca jelas kegelisahan di baliknya.
“Ais, Mbah Rara sudah siapkan kebaya untukmu. Warna lavender, katanya cocok dengan kulitmu. Besok Minggu kita coba di rumah, ya? Mbah juga mau lihat ukuran, siapa tahu perlu disesuaikan.”
“Coba” adalah kata yang halus untuk sebuah ujian. Aisyah tahu itu. Tapi setelah pertemuannya dengan Mbah Surti, ada sedikit keberanian baru dalam dirinya. Mungkin ini kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia serius mempelajari ‘bahasa’ sanggul, meski dalam caranya sendiri.
Minggu pagi, rumah keluarga besar terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya Bunda Arum dan Mbak Rara yang menunggu di ruang tengah. Sebuah setelan kebaya brokat lavender dengan kain jarik batik Sido Mukti berwarna senada telah terhampar di atas sofa. Di atas meja kecil, terdapat sebuah kotak kayu berukir berisi peralatan menyanggul: sisir bergagang kayu, minyak kemiri dalam botol kaca, semprotan air, jepit rambut berukuran besar, dan berbagai tusuk konde serta bunga-bunga melati tiruan.
“Ayo, nak, kita mulai,” ujar Mbak Rara, suaranya lebih lembut dari biasanya. Seolah hari ini adalah momen rekonsiliasi. “Dulu Mbah juga pertama kali disanggul oleh eyang putrimu di usia seperti kamu.”
Aisyah menggigit bibir. Ia masuk ke kamar mandi untuk mengganti pakaian. Kebaya itu ternyata pas di tubuhnya, memeluk lekuk dengan sempurna. Kain jarik yang dililitkan Bunda Arum membungkus pinggangnya dengan kencang, membuatnya harus menarik napas sedikit lebih dalam. Saat ia keluar, Mbak Rara mengangguk pelan, sebuah cahaya kepuasan sesaat melintas di matanya.
“Bagus. Sekarang, duduklah.” Mbak Rara menunjuk bangku pendek di depan cermin besar berbingkai kayu jati.
Aisyah duduk. Di cermin, ia melihat tiga perempuan: dirinya yang tegang, Bunda Arum yang berdiri di belakang dengan ekspresi cemas, dan Mbak Rara yang mulai dengan penuh konsentrasi mengambil sisir.
Prosesnya dimulai dengan ritualis. Mbak Rara membuka ikatan rambut Aisyah dengan lembut. “Rambutmu halus, tapi cukup tebal. Bagus untuk disanggul,” gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Ia mulai menyisir, gerakannya terampil dan penuh keyakinan. Setiap tarikan sisir terasa seperti sebuah klaim, menarik Aisyah masuk lebih dalam ke dalam ritual yang telah berusia berabad-abad.
Saat rambutnya sudah rapi, Mbak Rara mengambil semprotan air dan minyak kemiri. “Agar tidak kusut dan berkilau,” katanya. Aroma minyak kemiri yang khas memenuhi udara, membangkitkan memori masa kecil yang samar. Jari-jari Mbak Rara yang berusia namun masih lincah mulai mengepang, memutar, dan membentuk. Aisyah bisa melihat dalam cermin bagaimana sanggul mulai terbentuk di belakang kepalanya. Bentuknya rendah dan rapat, gelung tekuk yang klasik. Ia terpana. Ada sebuah keindahan yang tidak terbantahkan dalam presisi gerakan neneknya.
Tapi kemudian, ketegangan itu naik lagi. Rambut yang tadinya terurai kini hampir seluruhnya tertarik ke belakang, menampakkan seluruh garis wajah dan lehernya. Ia merasa sangat… terbuka.
“Bagus, tinggal sedikit lagi,” desis Mbak Rara, fokus. Sanggul inti sudah terbentuk. Sekarang tinggal memasang hiasan. Mbak Rara mengambil tusuk konde perak. “Sekarang, untuk memasang ini, bagian tengah sanggul harus rapat sempurna.”
Itu adalah saat yang dinanti-nanti dan juga ditakuti. Mbak Rara tanpa berpikir panjang, tangan kanannya meraih ujung kerudung Aisyah yang masih menutupi bahu dan lehernya. Dengan gerakan lembut tapi pasti, ia mulai menariknya ke bawah.
Sentuhan itu seperti setrum.
“Tidak!” teriak Aisyah reflek, tangannya membetot tangan neneknya. Ia berdiri begitu tiba-tiba, hingga bangku terdorong ke belakang dengan suara berdecit keras.
Suasana membeku.
Mbak Rara terkesiap, tangan yang memegang tusuk konde bergetar. Wajahnya yang semula penuh konsentrasi berubah menjadi kecewa yang mendalam, lalu menjadi dingin. Bunda Arum menutup mulutnya, matanya berlinang.
Aisyah terengah-engah, tangannya masih memegang erat ujung kerudungnya, menariknya kembali hingga menutupi lehernya sepenuhnya. Dadanya naik turun. Di cermin, pantulannya adalah seorang perempuan dengan separuh sanggul yang hampir sempurna, wajah pucat, dan mata penuh ketakutan. Ia tampak seperti sebuah karya yang gagal di tengah pengerjaan.
“Maaf, Mbah, aku… aku belum siap,” suara Aisyah bergetar.
“Belum siap?” suara Mbak Rara datar, namun mengandung sakit yang luar biasa. “Atau tidak mau? Aisyah, ini hanya kain.” Ia menunjuk kerudung itu. “Hanya untuk beberapa jam saja kau bisa melepasnya! Untuk menghormati keluargamu sendiri!”
“Ini bukan ‘hanya kain’ bagiku, Mbah!” bantah Aisyah, air mata mulai menggenang. “Ini adalah… ini adalah bagian dari diriku. Melepasnya di depan orang banyak, rasanya seperti… seperti menyuruhku telanjang.”
“Jadi menurutmu, semua perempuan nenek moyang kita yang bersanggul dan tidak berkerudung itu telanjang? Mereka tidak punya harga diri?” suara Mbak Rara mulai meninggi, getir. “Kau pikir keyakinanmu lebih tinggi dari leluhurmu sendiri?”
“Itu bukan maksudku!”
“Lalu apa?!” teriak Mbak Rara untuk pertama kalinya. Kesabarannya habis. “Aku sudah berusaha memahami pilihanmu. Tapi kau bahkan tidak memberi kami satu hari! Satu hari untuk menunjukkan bahwa kau masih peduli pada garis keturunan ini, pada warisan yang telah menjaga nama keluarga kita! Atau mungkin memang begitu? Kau malu menjadi bagian dari kami? Kau lebih nyaman bersembunyi di balik kain itu dan berpura-pura tidak punya akar?!”
Setiap kata seperti cambuk. Aisyah terguncang. Ia melihat sakit di mata neneknya yang lebih dalam dari sekadar penolakan terhadap sanggul. Itu adalah rasa sakit karena merasa ditolak, dianggap ketinggalan zaman, tidak dianggap relevan.
“Mbah Rara, jangan…” Bunda Arum mencoba menengahi, tetapi terlambat.
“Tidak,” kata Aisyah, suaranya lirih namun putus. Air mata mengalir deras. “Aku tidak bisa. Aku tidak bisa melakukan ini.” Ia tidak tahan melihat kekecewaan dan kemarahan di wajah neneknya. Ia tidak tahan melihat dirinya yang terpecah di cermin.
Dengan tangan gemetar, ia mulai melepaskan jepit-jepit rambut yang menahan sanggul setengah jadi itu. Rambutnya yang berminyak kemiri jatuh berantakan di bahu, menodai kebaya lavender yang indah. Ia bahkan tidak peduli. Ia berjalan terhuyung ke kamar mandi, berganti pakaian dengan cepat, meninggalkan kebaya yang tergeletak di lantai seperti kulit yang terkelupas.
Saat ia keluar, hanya Bunda Arum yang menunggu dengan mata merah. Mbak Rara sudah menghilang, kemungkinan ke kamarnya, mengunci diri dalam kekecewaan.
“Aisyah…” Bunda Arum mencoba memeluknya, tetapi Aisyah menghindar.
“Aku mau pulang dulu, Bun,” bisiknya, suara serak.
Ia berlari keluar dari rumah itu. Angin siang yang panas menghantam wajahnya yang basah. Ia terus berjalan tanpa arah, menghindari taksi atau angkutan. Ia perlu berjalan. Perlu menjauh.
Uji coba itu berantakan. Tidak ada yang menang. Mbak Rara terluka karena penolakannya. Dan dirinya? Ia merasa gagal total. Gagal menjadi cucu yang baik, gagal menjadi perempuan Jawa yang ‘benar’, dan bahkan gagal mempertahankan keyakinannya dengan cara yang elegan. Ia hanya menjadi seorang pelarian, dengan separuh sanggul yang hancur dan kerudung yang terasa seperti bendera kekalahan.
Mbah Surti bilang mencari bahasa sendiri. Tapi hari ini, bahasa yang keluar dari mulutnya hanyalah teriakan dan tangisan. Dan di kejauhan, bayangan sanggul yang anggun dan sempurna seolah tertawa getir, mengingatkannya bahwa mungkin, kedamaian antara dua dunia itu hanyalah ilusi.
Bab 5: Ruang Aman dan Ide Gila
Kaki Aisyah membawanya tanpa sadar ke suatu tempat yang sudah lama menjadi pelariannya: Sanggar Matahari, sebuah komunitas seni kecil di belakang pasar yang dikelola oleh seniman-seniman muda. Tempat itu berbau cat tua, kayu, dan kopi murah. Di sinilah, dulu, ia pertama kali merasa karyanya dipahami, bukan hanya dinilai.
Rendra, yang sedang asyik mengecat latar panggung miniatur untuk pementasan mendatang, adalah orang pertama yang melihatnya masuk. Wajah Aisyah yang pucat, mata bengkak, dan rambut yang masih berantakan serta sedikit berminyak kemiri langsung menarik perhatiannya. Tanpa banyak tanya, ia meletakkan kuasnya dan mendekat.
“Ais?” panggilnya lembut. “Kamu baik-baik saja?”
Pertanyaan sederhana itu bagai melepas bendungan. Air mata yang sudah tertahan selama perjalanan kembali mengalir. Aisyah hanya bisa menggeleng, menundukkan kepalanya sehingga kerudungnya yang kusut membentuk semacam tirai antara dirinya dan dunia.
Rendra tidak memaksa. Ia hanya mengambilkan bangku kayu dan secangkir teh hangat yang pahit. “Duduk. Minum. Nanti kalau mau cerita, cerita. Kalau enggak, ya nonton aku cat ini bentuk daun yang enggak jelas,” ujarnya, berusaha meredakan ketegangan.
Aisyah duduk, menghirup teh. Kehangatan cangkir di telapak tangannya sedikit menenangkan. Ia menatap Rendra yang kembali ke pekerjaannya, sibuk dengan detail-detail kecil. Ada sesuatu yang menenangkan dalam kesibukan orang lain yang tidak berhubungan dengan masalahnya.
“Aku tadi… bertengkar hebat dengan nenekku,” akhirnya suaranya pecah, serak.
Rendra berhenti mengecat, tapi tidak menoleh. Memberinya ruang untuk bicara.
“Aku dicoba disanggul. Untuk pernikahan. Dan… aku panik. Aku menolak untuk melepas kerudungku. Nenekku bilang aku malu dengan akar keluarga sendiri.” Ia menceritakan segalanya, dari tekanan undangan, risetnya, pertemuan dengan Mbah Surti yang memberi harapan, hingga uji coba berantakan yang berakhir dengan kata-kata pedih dan pelariannya.
“Jadi, sekarang aku merasa seperti pengkhianat dari kedua belah pihak,” simpul Aisyah, lelah. “Aku mengkhianati keluarga karena tidak mau mematuhi aturan. Dan aku merasa mengkhianati diriku sendiri karena… karena ternyata keyakinanku tidak cukup kuat untuk menghadapi konfrontasi seperti ini dengan tenang. Aku cuma bisa lari.”
Rendra akhirnya menoleh, menyeka tangannya yang penuh cat di celemek. “Aisyah, kamu tahu di teater, saat ada konflik yang terlalu besar untuk diucapkan?”
Aisyah mengangkat bahu.
“Kita bikin metafora. Kita bikin adegan bisu. Atau kita ubah konflik itu menjadi sebuah benda, sebuah set panggung, yang bisa dilihat dan dirasakan penonton tanpa perlu dialog.” Rendra mendekat, matanya berbinar dengan ide yang tiba-tiba muncul. “Konflikmu ini… ini bukan kekurangan, Ais. Ini adalah bahan mentah yang luar biasa. Murni. Nyata.”
“Apa maksudmu?”
“Instalasi tugas akhirmu. ‘Dinding yang Bernapas’. Itu kan tentang sesuatu yang kaku vs sesuatu yang cair, kan? Tapi masih abstrak.” Rendra berdiri, mulai berjalan mondar-mandir dengan energi baru. “Bayangkan jika kau mengolah konflik pribadimu ini menjadi karya. Jika kau membuat ruang di mana kerudung dan sanggul itu tidak bertarung, tetapi… berdialog. Atau bahkan, menari bersama dalam keheningan.”
Gagasan itu seperti kilat di tengah kegelapan.
“Tapi… bagaimana?” bisik Aisyah, tertarik namun ragu.
“Kau sendiri yang bilang, setelah ketemu Mbah Surti, kau merasa bisa menemukan ‘bahasa sendiri’,” Rendra terus memicu. “Nah, seniman itu tugasnya menemukan bahasa baru untuk hal-hal yang sulit diucapkan. Daripada kau terjepit di antara dua pilihan, kenapa kau tidak menciptakan pilihan ketiga? Di atas kanvas, di ruang pamer? Jadikan tubuhmu, konflikmu, sebagai medium. Bukan untuk menyelesaikan masalah keluarga dalam satu malam, tapi untuk menunjukkan kompleksitasnya. Untuk membuat orang yang melihat—termasuk mungkin Mbak Raramu—bisa melihat pergulatanmu bukan sebagai pembangkangan, tapi sebagai… proses pencarian yang serius.”
Aisyah terdiam. Pikirannya bekerja cepat. Karya instalasinya yang selama ini masih berupa konsep abstrak tentang batas dan kebebasan, tiba-tiba mendapat bentuk yang sangat konkret. Jaring kasa, kain transparan… bisa menjadi metafora rambut, kain kerudung, batas yang tembus pandang. Ia bisa membuat serangkaian ‘sanggul’ dari material yang tak terduga. Bukan untuk menggantikan yang asli, tetapi untuk membahasanya.
“Seperti… sebuah pertanyaan tiga dimensi,” gumam Aisyah perlahan.
“Tepat!” Rendra tersenyum. “Dan siapa tahu, dengan membuat karya ini, kau justru menemukan jawaban untuk dirimu sendiri. Seni kan sering begitu.”
Saat itulah, telepon Aisyah bergetar. Sebuah pesan masuk, bukan dari Bunda Arum atau Mbak Rara, melainkan dari sebuah nomor tak dikenal. Isinya sederhana:
“Anakku Aisyah, tadi ada yang kirim paket kecil untukmu ke rumahku. Katanya dari Mbah Surti. Kalau mau mengambil, silakan kapan saja. – Tante Sari (tetangga Mbah Surti)”
Mbah Surti. Nenek bijak itu seolah merasakan kekalahannya dari kejauhan. Tanpa berpikir dua kali, Aisyah pamit pada Rendra. Ide gila itu sudah tertanam, tapi mungkin paket itu mengandung petunjuk lebih lanjut.
Perjalanan ke rumah Mbah Surti kali ini terasa berbeda. Ada tujuan kecil yang jelas: mengambil paket. Rumah itu masih sama, tenang dan harum. Tante Sari, tetangga yang baik hati, memberikan sebuah bungkusan kecil dibungkus kertas coklat dan diikat tali rafia.
Di dalam mobil, dengan jantung berdebar, Aisyah membukanya. Tidak ada catatan. Hanya sebuah benda yang dibungkus kain mori halus. Saat dibuka, ia menemukan sebuah cundhuk mentul—tusuk konde tradisional yang sederhana, terbuat dari kayu cendana tua yang harum, dengan ujung berbentuk kuncup bunga yang belum mekar. Berbeda dengan tusuk konde mewah berukir yang sering ia lihat di buku. Ini sederhana, kuat, dan terasa sangat… tulus.
Dan di balik tusuk konde itu, terbungkus rapi, ada secarik kertas tipis dari buku catatan. Tulisan tangan Mbah Surti yang sedikit gemetar namun jelas:
“Nak, dulu pertama kali saya belajar menyanggul, yang diajarkan guru saya bukan cara mengikat rambut, tetapi cara ‘memegang’ rambut. Hormati rambutnya, pahami arah tumbuhnya, baru bentuk. Jangan melawan alamnya.
“Mungkin yang kau cari bukan cara memakai sanggul atau memakai kerudung. Tapi cara ‘memegang’ kedua warisan itu dalam genggaman hidupmu. Hormati keduanya. Pahami arahnya. Jangan melawan alam jiwamu.
“Kuncup bunga ini belum mekar. Seperti jawabanmu. Tapi ia sudah ada bentuknya. Sabar.”
Aisyah memegang tusuk konde kayu itu erat-erat. Air mata lagi. Tapi kali ini, bukan air mata keputusasaan. Ini air mata karena merasa dipahami, diantar, oleh seseorang yang telah melalui jalan yang mungkin mirip.
Ia melihat pantulannya di kaca spion. Rambutnya masih berantakan, bekas minyak kemiri dan kegagalan. Tapi di tangannya, ada sebuah alat dari tradisi yang justru memberinya izin untuk mencari jalan sendiri.
Ide gila Rendra dan kebijakan sederhana Mbah Surti bertemu di benaknya. Ia tidak harus memilih. Ia harus mencipta. Mencipta sebuah jawaban visual, sebuah pernyataan diri yang bukan “ini ATAU itu”, tetapi “ini DAN itu, dan inilah rasanya”.
Dengan tekad baru, ia menyalakan mesin mobil. Tujuannya bukan lagi kos atau rumah keluarga. Tujuannya adalah toko material seni terdekat. Ia butuh lebih banyak kain, kawat, benang, alat perekat. Ia punya karya untuk disempurnakan. Ia punya pertanyaan besar yang harus diwujudkan.
“RAGAM: Dari Leher yang Sama.” Judul itu tiba-tiba muncul di kepalanya, jelas dan kuat. Ini bukan lagi “Dinding yang Bernapas”. Ini lebih personal, lebih berani. Ini adalah pernyataan bahwa semua keragaman itu—sanggul, kerudung, tekanan, keyakinan, cinta, kewajiban—bersumber dari leher yang sama: dirinya.
Perasaan terpojok mulai berganti dengan semangat pencipta. Ia mungkin belum punya solusi untuk pernikahan Gendhis. Tapi ia sekarang punya sebuah misi: untuk membuat konfliknya menjadi sesuatu yang bisa dilihat, disentuh, dan mudah-mudahan, dipahami. Bahkan oleh sepasang mata tua yang penuh kekecewaan. Itulah harapannya.
Bab 6: Menemukan Bahasa Baru
Hari-hari setelahnya diisi dengan ritme yang berbeda. Jika sebelumnya Aisyah terbebani oleh tenggat waktu pernikahan Gendhis, kini ia memiliki tenggat waktu lain yang ia pilih sendiri: pameran tugas akhir. Dua pekan itu ia habiskan dalam sebuah gelembung kreatif yang intens. Kosnya yang sederhana berubah menjadi laboratorium eksperimen yang kacau-balau.
Di lantai berserakan gulungan kain berbagai tekstur: sifon, linen, sutra, bahkan kain bludru dan jaring kasa. Di meja kerjanya, berbagai jenis benang, kawat tembaga fleksibel, lem tembak, dan cat akrilik berjejalan dengan tusuk konde pemberian Mbah Surti dan buku-buku referensi sanggul.
Ide awal dari obrolan dengan Rendra mulai menemukan bentuk. Aisyah memutuskan untuk membuat serangkaian torso—patung tubuh dari dada hingga kepala—sebagai kanvas utamanya. Torso-torso itu ia buat dari kain yang direndam dalam campuran lem dan air, lalu dibentuk di atas maneken, menciptakan bentuk yang keras namun tetap organik, seperti kulit kedua yang kosong.
Pada torso pertama, ia membuat “sanggul” dari anyaman benang katun putih yang ketat dan rapi. Namun, bila dilihat lebih dekat, anyaman benang itu sebenarnya membentuk pola kaligrafi Arab yang bertuliskan “Al-Haqq” (Kebenaran). Sanggul ini ia beri judul “Gelung Sabda”.
Pada torso kedua, ia mengambil lembaran foto kopi hitam-putih—foto-foto arsip keluarga yang ia kumpulkan diam-diam dari Bunda Arum: foto Mbak Rara muda menari, foto eyang buyutnya dengan sanggul tinggi, foto ibunya saat gadis. Foto-foto itu ia robek kecil, lalu direkatkan membentuk lekukan sanggul yang pecah dan tidak sempurna, seperti memori yang terfragmentasi. Ini adalah “Sanggul Ingatan”.
Eksperimen paling personal dilakukan di depan cermin kamar mandinya yang panjang. Dengan tripod dan kamera ponselnya, ia merekam sebuah video performatif. Ia berdiri membelakangi kamera, mengenakan kaus hitam polos. Dengan gerakan lambat dan penuh kesadaran, ia mulai merangkai sebuah “sanggul” di atas kepalanya yang tetap berkerudung. Ia tidak menggunakan rambut asli, melainkan sehelai syal panjang berwarna krem—warna kerudung favoritnya—yang ia anyam dan putar, dibentuk dengan jepit dan konde, menciptakan siluet sanggul yang samar, lunak, dan menyatu dengan kerudung itu sendiri. Prosesnya sunyi, meditatif, dan penuh usaha. Di akhir video, ia menancapkan cundhuk mentul pemberian Mbah Surti ke dalam anyaman syal itu. Hasilnya adalah sebuah bentuk baru: bukan sanggul tradisional, bukan pula kerudung biasa, tetapi sebuah mahkota hibrida yang lahir dari pergulatan.
Video itu ia proyeksikan ke dinding di belakang barisan torso, menciptakan ilusi bahwa sanggul-sanggul di dinding sedang ‘ditumbuhkan’ oleh gerakan di layar. Ia menyebut video ini “Merangkai Diatas Diri”.
Suatu sore, saat ia asyik menganyam kawat tembaga dan manik-manik kaca untuk torso ketiga, teleponnya berdering. Bunda Arum.
“Ais,” suara ibunya terdengar lelah. “Mbah Rara… kondisinya kurang baik. Sedikit demam. Dokter bilang karena stres. Dia… masih sangat kecewa.”
Dada Aisyah sesak. Rasa bersalah yang telah ia kubur sementara di bawah tumpukan karya seni kembali menyeruak.
“Tapi, dia tadi bertanya,” lanjut Bunda Arum, suaranya sedikit bergetar penuh harap. “Dia bertanya… ‘Aisyah dan karya tugas akhirnya bagaimana?’.”
Pertanyaan itu mengguncang Aisyah. Di balik kekecewaan yang mendalam, Mbak Rara masih mengingatnya. Masih peduli pada dunianya.
“Aku… sedang mengerjakannya, Bun. Aku ingin sekali menunjukkan pada Mbah,” jawab Aisyah, suaranya penuh keyakinan yang baru.
“Tunjukkan apa, Nak? Bunda tidak mau kamu dan Mbah semakin renggang.”
“Aku ingin menunjukkan bahwa aku tidak mengabaikan warisannya. Bahwa aku… sedang berusaha menghormatinya, dengan caraku. Lewat seni.”
Di ujung telepon, Bunda Arum terdiam lama. “Baik, Nak. Bunda percaya padamu. Jaga kesehatan.”
Setelah telepon usai, Aisyah merasa dorongan yang lebih kuat. Ia butuh satu elemen terakhir, sesuatu yang menjadi inti dari pertanyaan “bahasa sendiri”. Ia butuh pergi ke sumbernya. Bukan untuk meminta izin, tetapi untuk mencari ketenangan.
Esok paginya, ia pergi ke makam leluhur keluarganya, sebuah area yang terpelihara di kompleks pemakaman umum. Di bawah naungan pohon beringin yang rindang, batu-batu nisan kuno berdiri dengan nama-nama yang ia dengar dalam cerita Mbak Rara. Suasana hening, jauh dari kebisingan kota dan konflik.
Ia duduk di depan nisan eyang buyutnya, seorang perempuan yang dikenal sebagai penjaga tradisi tata busana di zamannya. Angin sepoi-sepoi berbisik di antara daun.
“Aku tidak tahu apakah ini menghormati atau justru mendurhakai, Eyang,” bisiknya pelan, seolah berbicara pada batu nisan. “Aku cinta keluarga kami. Aku kagum pada warisan keanggunan yang kalian rawat. Tapi aku juga mencintai keyakinan yang memberiku kedamaian. Apakah aku harus memilih salah satu untuk membuktikan cintaku?”
Tentu saja tidak ada jawaban. Hanya sunyi yang merangkul.
Ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan tusuk konde kayu dan sehelai syal. Di tempat yang tenang ini, ia mencoba lagi merangkai syalnya di atas kerudung, meniru gerakan dalam videonya. Di sini, tanpa tekanan mata siapa pun, prosesnya terasa alami. Ia bukan sedang membela diri atau memberontak. Ia sedang… bereksperimen dengan identitas.
Saat syal membentuk lekukan sederhana di belakang kepalanya, tiba-tiba ia teringat kata-kata Mbah Surti: “Jangan melawan alamnya.” Alam rambut. Alam keyakinan. Alam budaya. Mungkin, selama ini ia terlalu memaksakan diri untuk ‘memilih’, padahal yang ia butuhkan adalah menemukan bagaimana ketiganya bisa hidup dalam harmoni yang baru, yang sesuai dengan zamannya.
Ia meninggalkan makam dengan perasaan lebih ringan. Ia tidak mendapatkan jawaban verbal, tetapi ia mendapatkan sebuah kejelasan batin: ia tidak sendirian. Ia adalah bagian dari rantai panjang perempuan-perempuan dalam keluarganya, yang masing-masing juga pasti bergumul dengan tuntutan zamannya. Mungkin tugasnya bukan untuk memutuskan rantai itu, tetapi untuk menambahkan mata rantai baru yang merefleksikan zamannya.
Kembali di kos, dengan ketenangan baru itu, karya instalasinya menemukan jiwa yang lebih dalam. Torso terakhir yang ia buat adalah yang paling sederhana dan paling kuat. Sebuah torso polos dari kain linen. Di atasnya, ia tidak membuat sanggul sama sekali. Hanya ada satu garis horizon yang dilukis dengan cat emas tipis, melingkari ‘leher’ patung itu. Dan dari garis itu, menjulur seutas tali panjang dari anyaman benang merah dan benang putih yang dipilin menjadi satu, terjuntai ke lantai. Karyanya berjudul “Bening: Titik Berangkat”.
Karya ini adalah pernyataan akhirnya. Sebuah pengakuan bahwa konflik itu nyata (pilinan merah-putih), bahwa ia dimulai dari titik yang sama (leher, diri), tetapi bahwa jawabannya mungkin bukan pada bentuk akhir yang sempurna, melainkan pada keberanian untuk memulai anyaman, untuk merangkai, dan membiarkan prosesnya sendiri menjadi mahkota.
Malam sebelum pameran, Aisyah memandang karya-karyanya yang telah selesai di ruang kosnya. Sebuah keluarga kecil dari torso-torso bisu yang menyimpan teriakannya, pertanyaannya, dan harapannya. Ia menarik napas dalam.
Ia belum tahu apa yang akan terjadi di pameran besok. Apakah Mbak Rara akan datang? Apakah ia akan mengerti? Yang ia tahu, untuk pertama kalinya, ia telah berhasil menerjemahkan pergulatannya menjadi sebuah bahasa yang bisa ia pahami: bahasa bentuk, tekstur, dan ruang.
Bahasa barunya masih terbata-bata, masih eksperimental. Tapi setidaknya, ia sudah mulai berbicara. Dan kadang, berpikir Aisyah sambil memegang cundhuk mentul yang hangat, dalam seni, yang terpenting bukanlah kesimpulan, melainkan kejujuran dalam proses bertanya.
Bab 7: Pameran dan Pertunjukan
Hari itu kampus seni berdenyut dengan energi yang berbeda. Lorong-lorong biasa dijejali papan nama, brosur, dan aroma kopi gratis. Suara riuh rendah pengunjung, kritikus, dosen, dan keluarga mahasiswa bergema di ruang pamer utama yang biasanya sunyi. Untuk sebagian besar peserta, ini adalah puncak perjuangan akademis. Untuk Aisyah, ini lebih dari itu: ini adalah pengadilan sekaligus perayaan atas pergulatan batinnya selama sebulan terakhir.
Ruangan instalasinya, sebuah ruang kecil di sayap timur galeri, telah ia sulap menjadi sebuah ruang kontemplasi. Lampu sorot lembut menyinari lima torso yang ia susun setengah melingkar. Di dinding belakang, video “Merangkai Diatas Diri” diproyeksikan dalam loop sunyi, memperlihatkan proses pembentukan sanggul-kerudung hibrida itu dengan gerakan yang hampir ritualistik. Suara latar yang ia pilih hanyalah desahan napasnya sendiri dan suara gesekan kain yang halus.
Ia sendiri berdiri di sudut, mengenakan pakaian sederhana: kaus hitam, celana jeans, dan kerudung sutra warna tanah liat. Tangannya basah oleh keringat dingin. Matanya terus mengawasi pintu masuk, menyisir setiap wajah yang masuk.
Rendra datang lebih dulu, bersama beberapa anggota kelompok teaternya. Mereka diam seribu bahasa saat menyaksikan karya itu, berjalan perlahan dari satu torso ke torso lainnya. Rendra menangkap pandangan Aisyah dan memberinya anggukan kecil, sebuah isyarat “kerjamu bagus”.
Lalu, datanglah Bunda Arum. Ibunya terlihat tegang, matanya langsung mencari Aisyah. Saat bertemu pandang, Bunda Arum tersenyum getir, lalu matanya beralih ke karya-karya di ruangan itu. Ia berjalan mendekati “Sanggul Ingatan”, torso dengan foto-foto keluarga yang terpecah. Jarinya hampir-hampir menyentuh foto Mbak Rara muda yang tersenyum lurus ke kamera. Bibir Bunda Arum bergetar, ia menutupnya dengan tangan.
Tapi yang ditunggu-tunggu Aisyah belum juga datang. Jam terus berjalan. Rasa cemas mulai bercampur dengan kekecewaan. Mungkin Mbak Rara memang tidak akan datang. Mungkin luka itu terlalu dalam.
Saat pameran hampir memasuki jam akhir, kerumunan di luar ruangannya tiba-tiba sedikit berdesakan. Beberapa pengunjung menengok, lalu memberi jalan. Dan di sana, di balik kerumunan, muncul sosok yang tegak meski terlihat lebih kurus dari biasanya.
Mbak Rara.
Ia datang didampingi oleh Bunda Arum yang buru-buru menyambutnya. Neneknya itu mengenakan kebaya sutra sederhana berwarna abu-abu, rambutnya yang putih disanggul rapi dengan gelung tekuk. Wajahnya pucat, tetapi matanya—mata yang sama tajamnya—langsung menyapu ruangan, berhenti sejenak pada Aisyah yang membeku di tempatnya, lalu beralih ke karya-karya di hadapannya.
Aisyah menahan napas. Ia melihat neneknya berjalan perlahan, sangat perlahan, mendekati barisan torso. Ia berhenti di depan “Gelung Sabda”, sanggul anyaman benang kaligrafi. Mbak Rara membungkuk, matanya menyipit memperhatikan detail anyaman. Jari-jarinya yang keriput hampir menyentuh, tetapi berhenti di udara, seolah takut merusak mantra yang terbentuk di sana. Wajahnya tidak terbaca.
Ia bergeser ke “Sanggul Ingatan”. Di sinilah, untuk pertama kalinya, ekspresi Mbak Rara berubah. Napasnya seperti tersendat saat melihat foto-foto itu, fragmen-fragmen dari hidupnya, dari garis keturunannya, disusun kembali menjadi bentuk sanggul yang retak. Ia melihat lebih dekat, mengenali setiap wajah, setiap momen. Tangannya yang menggenggam sapu tangan sutra di pinggangnya mengeras.
Kemudian, ia sampai di torso terakhir, “Bening: Titik Berangkat”. Hanya torso polos dengan garis emas dan pilinan benang merah-putih. Mbak Rara memandangnya lama. Sangat lama. Aisyah bisa melihat kerongkongan neneknya bergerak, seperti menelan sesuatu yang pahit atau… sesuatu yang sulit diucapkan.
Lalu, Mbak Rara menoleh. Bukan kepada Aisyah, tetapi kepada dinding di belakangnya, di mana video performatifnya diproyeksikan. Di layar, Aisyah versi hitam putih sedang dengan sabar, penuh konsentrasi, merangkai syalnya di atas kerudung. Gerakannya tidak terburu-buru, tidak penuh amarah, tetapi penuh upaya. Penuh penghormatan terhadap materialnya sendiri.
Mbak Rara berdiri diam menyaksikan seluruh loop video itu, dari awal hingga akhir, saat cundhuk mentul tertancap dan sosok di video berdiri tegak, dengan siluet baru di kepalanya. Saat video mulai mengulang, Mbak Rara memejamkan mata. Dadanya naik turun sekali.
Ruang di sekitar mereka seolah menghilang. Suara riuh di luar menjadi gemuruh yang jauh. Hanya ada nenek, cucu, dan karya-karya bisu yang menjadi juru bicara.
Bunda Arum mendekat, ingin memegangi lengannya, tetapi Mbak Rara mengangkat tangan halus, menolak. Ia membuka mata, dan kali ini, ia menatap langsung Aisyah.
Sorot matanya tidak lagi penuh kekecewaan atau kemarahan. Yang ada adalah kelelahan yang sangat dalam, dan… sebuah pertanyaan yang terbuka.
Ia berjalan mendekati Aisyah, langkahnya pelan namun pasti. Berdiri di hadapan cucunya, ia memandanginya dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu kembali ke matanya.
“Inikah… bahasamu?” suara Mbak Rara terdengar serak, nyaris berbisik.
Aisyah hanya bisa mengangguk, tenggorokannya terasa kering.
Mbak Rara mengangguk pelan, seolah memahami sesuatu yang sangat besar. Ia memandang sekali lagi ke sekeliling ruangan, menyerap setiap detail, setiap upaya yang tercurah dalam karya-karya itu.
“Kau…” ia memulai, suaranya masih lirih, “Kau merobek foto-foto kita.”
“Aku… menyatukannya kembali, Mbah. Dalam bentuk baru,” jawab Aisyah, suaranya bergetar.
“Bentuk yang patah-patah.”
“Karena ingatanku tentang semua ini… memang belum utuh. Tapi aku sedang berusaha menyusunnya.”
Diam lagi. Udara terasa padat.
“Dan itu,” Mbak Rara menunjuk video, “Apa yang kau lakukan di sana? Itu bukan sanggul.”
“Bukan sanggul seperti yang Mbah ajarkan. Tapi… itu usahaku untuk merangkai. Untuk tidak melepas, tetapi juga… untuk tidak menolak.”
Mbak Rara menarik napas panjang. Ia mengulurkan tangannya, tidak untuk menampar atau memeluk, tetapi untuk menyentuh lengan Aisyah. Sentuhan itu ringan, dingin, namun terasa seperti jembatan yang rapuh akhirnya terjangkau.
“Aku melihat usahamu,” ucap Mbak Rara, suaranya lebih jelas sekarang. “Aku tidak mengerti semuanya. Bentuk-bentuk ini… asing bagiku.” Ia berhenti, mencari kata. “Tapi… aku melihat rasa-nya. Aku melihat bahwa ini bukan dibuat dengan tangan yang malas atau hati yang membenci.”
Air mata yang selama ini ditahan Aisyah akhirnya jatuh. Itu saja. Itu sudah lebih dari cukup. Pengakuan bahwa neneknya ‘melihat’ usahanya.
“Aku tidak malu pada leluhur kita, Mbah,” bisik Aisyah, air mata mengalir deras. “Aku sedang berusaha menemukan cara… untuk tetap menjadi bagian dari mereka, tanpa harus berhenti menjadi diriku.”
Mbak Rara memejamkan mata lagi, seolah kata-kata itu perlu dicerna dengan hati. Saat ia membuka mata, ada kelembutan yang sangat samar, seperti kabut di pagi hari yang mulai tersibak.
“Karya ini… apa judulnya?” tanyanya.
“RAGAM: Dari Leher yang Sama,” jawab Aisyah.
Mbak Rara mengulangi judul itu dalam hati, matanya lagi-lagi berkeliling ruangan. “Dari leher yang sama,” gumamnya. Ia mengangguk, sangat pelan. Lalu, tanpa kata-kata lagi, ia memutar tubuh, dan berjalan perlahan meninggalkan ruang pamer, didampingi Bunda Arum yang juga berkaca-kaca.
Aisyah berdiri di tempatnya, lemas. Tubuhnya gemetar, tetapi di dadanya ada kelegaan yang luar biasa. Ia tidak dimengerti sepenuhnya. Ia tidak diberi restu secara verbal. Tapi ia telah ‘didengarkan’ oleh orang yang paling ia takuti penilaiannya. Karyanya telah menjadi pembicara yang lebih fasih dari mulutnya sendiri.
Rendra mendekat, meletakkan tangan di bahunya. “Luarbiasa, Ais. Itu… itu adalah pertunjukan yang paling mengharukan yang pernah kulihat.”
Aisyah tersenyum lemas, masih menatap pintu kosong tempat neneknya menghilang. Pertunjukannya mungkin sudah selesai. Tapi dialognya, barangkali, baru saja dimulai. Ia telah membuka sebuah pintu. Sekarang, ia harus menunggu, apakah dari balik pintu itu akan ada tanggapan, atau setidaknya, keheningan yang lebih damai.
Bab 8: Resolusi yang Tidak Sempurna, namun Tulus
Ketenangan setelah pameran adalah jenis ketenangan yang baru. Bukan ketenangan karena konflik selesai, tetapi karena badai hebat telah berlalu, menyisakan lanskap yang berubah dan udara yang lebih jernih untuk bernapas. Pujian dosen dan rekan-rekan seniman di kampus memudar menjadi latar belakang. Yang terus terngiang di kepala Aisyah adalah tatapan Mbak Rara di ruang pamer: bingung, terluka, tetapi juga… terbuka.
Beberapa hari setelah pameran, telepon dari Bunda Arum kembali berdering. Suara ibunya kali ini lebih ringan, seperti seseorang yang baru saja meletakkan beban berat.
“Ais, Mbah Rara minta kamu datang. Hanya berdua. Besok sore.”
Jantung Aisyah berdebar kencang. Ini bukan undangan keluarga. Ini adalah pertemuan diplomatik.
Keesokan sorenya, ia berdiri lagi di depan rumah keluarga besar. Namun kali ini, tidak ada kebaya lavender atau kotak perias yang menunggu. Hanya aroma melati yang sama dan keheningan yang berbeda.
Mbak Rara menunggu di pendapa, duduk di kursi kayunya yang biasa. Di depannya, di atas meja kecil, hanya ada dua gelas teh panas dan sebuah kotak kayu berukir yang ia kenal baik—kotak tempat neneknya menyimpan perhiasan dan benda berharganya.
“Duduklah,” ujar Mbak Rara, suaranya datar namun tanpa duri.
Aisyah duduk, tangannya berkeringat di pangkuan.
“Karyamu…” Mbak Rara memulai, menatap gelas tehnya. “Aku sudah pikirkan. Dan aku sudah tanyakan pada beberapa kenalan yang mengerti seni modern.” Ia mengangkat mata, bertemu pandangan Aisyah. “Mereka bilang itu ‘berani’. Mereka bilang itu ‘personal’. Mereka bilang banyak hal yang tidak sepenuhnya aku pahami.”
Aisyah menunggu, menahan napas.
“Tapi satu hal yang aku pahami,” lanjut Mbak Rara, suaranya sedikit bergetar. “Adalah bahwa kau tidak membuat karya itu dengan hati yang sembrono. Kau merobek foto kita, ya. Tapi kau juga merangkainya. Kau tidak menolak sanggul, kau… mengolahnya. Dalam bahasamu yang asing itu.”
“Aku tidak bermaksud menyakiti, Mbah.”
“Aku tahu.” Dua kata itu diucapkan dengan usaha. “Aku melihat video itu berulang kali di kepalaku. Gerakan tanganmu. Sabar. Seperti… seperti sedang memegang sesuatu yang rapuh. Bukan seperti anak muda yang marah dan ingin menghancurkan.”
Mbak Rara mengambil napas dalam. “Selama ini, aku pikir kau malu pada kami. Pada sanggul, pada tata krama, pada semua yang kubanggakan. Tapi di karya itu, aku tidak melihat rasa malu. Aku melihat… kebingungan. Pencarian.” Ia menatap Aisyah tajam. “Seperti dulu, waktu aku muda, mencoba mencari caraku sendiri di antara aturan istana yang begitu ketat.”
Pengakuan itu membuat Aisyah tercekat. Ia tidak pernah membayangkan Mbak Rara pernah merasakan hal yang sama.
“Aku tidak bisa bilang aku setuju dengan caramu,” kata Mbak Rara tegas. “Bentuk-bentuk itu masih terasa aneh bagiku. Tapi…” Ia membuka kotak kayu di depannya. Dari dalam, ia mengambil sebuah benda yang dibungkus kain beludru hitam. Dengan hati-hati ia membukanya, mengeluarkan sebuah tusuk konde.
Bukan tusuk konde sembarangan. Ini terbuat dari perak tua, dengan ukiran rumit berupa sulur-sulur dan bunga melati yang sangat detail. Di ujungnya, ada sebuah batu kecubung kecil yang memantulkan cahaya lembut. Tusuk konde ini terlihat tua, berharga, dan penuh makna.
“Ini milik eyang putrimu,” ucap Mbak Rara, suaranya lembut penuh kenangan. “Dia yang mengajarkanku menari. Dia yang pertama kali menyanggulku untuk pentas di hadapan Sultan.” Ia memandang tusuk konde itu dengan mata berkaca-kaca, lalu mengulurkannya ke arah Aisyah. “Dulu, aku ingin memberikannya kepadamu saat kau dewasa, saat kau pertama kali bersanggul dengan sempurna untuk acara penting.”
Aisyah menatap tusuk konde yang terulur itu, tak berani menyentuhnya.
“Tapi mungkin, caraku menunggu ‘kesempurnaan’ itu salah,” bisik Mbak Rara. “Mungkin, yang lebih penting adalah niat untuk merangkai, bukan hasil akhir yang sesuai gambarku.” Ia mendorong tusuk konde itu sedikit lebih dekat. “Ambilah. Ini untukmu. Untuk kapan saja kau merasa… kau butuh menghubungkan dirimu dengan garis kami. Tidak harus dipakai di sanggul. Pakailah sesuai bahasamu.”
Dengan tangan gemetar, Aisyah menerima tusuk konde itu. Berat. Dingin di awal, lalu perlahan menghangat di telapak tangannya. Ini bukan sekadar perhiasan. Ini adalah gencatan senjata. Ini adalah pengakuan. Bahwa perjalanannya diakui, meski tujuannya belum sepenuhnya dipahami.
“Terima kasih, Mbah,” isak Aisyah, air mata menetes mengenai punggung tangannya yang memegang erat tusuk konde. “Ini… sangat berarti.”
Mbak Rara mengangguk, juga menyeka sudut matanya dengan sapu tangan. “Untuk pernikahan Gendhis…” Ia berhenti, seolah memilih kata-kata dengan sangat hati-hati. “Aku tidak akan memaksamu lagi. Tapi tolong, hadirlah. Sebagai cucu keluarga ini. Dengan caramu yang… sopan.”
Itu bukan restu penuh. Itu adalah kompromi. Sebuah jalan tengah. Dan untuk saat ini, itu lebih dari cukup.
Hari pernikahan Gendhis tiba. Balai pertemuan bernuansa Jawa dipadati keluarga besar, kerabat, dan undangan yang semuanya berpakaian adat lengkap. Lautan kebaya, kain jarik, dan sanggul yang megah. Suara gamelan mengalun lembut.
Saat Aisyah masuk bersama Bunda Arum dan ayahnya, beberapa pasang mata langsung tertuju padanya. Desis-desis samar mungkin berhembus. Karena Aisyah tidak datang dengan sanggul tinggi atau rambut tersisir rapi.
Ia datang dengan kebaya. Kebaya sutra lurus berwarna krem muda, dipadu dengan kain jarik batik Sido Mukti berwarna senada. Tapi di atasnya, ia tidak meninggalkan kerudungnya. Kerudung itu terbuat dari sutra tipis berwarna sama persis dengan kebayanya, dipotong dan dijahit dengan begitu rupa sehingga jatuh anggun di bahu dan dada. Dan yang menjadi pusat perhatian: di bagian belakang, kerudung sutra itu disusun dan diikat dengan teknik khusus, dibentuk membangun volume lembut yang menyerupai bentuk sanggul boko yang rendah dan sederhana. Di tengah anyaman sutra itu, berkilauan dua tusuk konde: cundhuk mentul kayu cendana pemberian Mbah Surti di sisi kiri, dan tusuk konde perak bermata kecubung pemberian Mbak Rara di sisi kanan.
Ia tidak menyanggul rambutnya. Rambutnya masih tersembunyi rapi di balik kain. Tapi ia telah membuat siluet sanggul dari kerudungnya sendiri. Sebuah sintesis. Sebuah pernyataan diam: Aku menghormati bentuknya, tapi dengan bahanku sendiri.
Dari seberang ruangan, di tempat keluarga inti duduk, Mbak Rara melihatnya. Nenek itu terdiam sejenak, matanya menyapu penampilan cucunya dari kepala hingga kaki. Lalu, sangat perlahan, sebuah anggukan hampir tak terlihat diberikan. Bukan senyum. Bukan pelukan. Tapi sebuah anggukan. Sebuah pengakuan bahwa Aisyah hadir, dengan caranya, dan caranya itu tidak melanggar kesopanan. Bahkan, ada keanggunan tersendiri di dalamnya—keanggunan yang lahir dari kejujuran.
Sepanjang acara, Aisyah merasa lebih ringan. Ia tidak lagi merasa seperti penyusup atau pemberontak. Ia merasa seperti dirinya sendiri, yang sedang belajar berdiri di tengah dua dunia tanpa memihak sepenuhnya pada salah satunya.
Malam setelah resepsi, Aisyah berdiri di balkon kosnya. Kota di bawahnya berkelip-kelip, hidup dengan ritmenya sendiri yang tak pernah berhenti. Di tangannya, ia masih memegang kedua tusuk konde: yang sederhana dari kayu, dan yang rumit dari perak.
“Merangkai Diatas Diri,” gumannya, mengingat judul videonya.
Ia menyadari, perjalanannya belum selesai. Besok, atau lusa, akan ada lagi tantangan, lagi pertanyaan tentang identitas dan kesetiaan. Tapi malam ini, ia merasa telah memenangkan sesuatu yang penting: sebuah kosakata baru.
Ia tidak lagi terjebak dalam “Kerudung ATAU Sanggul”. Ia kini memiliki kata kerja baru: merangkai. Memilih benang-benang dari warisan yang ia terima, memilih pola dari keyakinan yang ia anut, dan mencoba menjalinnya menjadi sebuah bentuk yang bisa ia jalani.
Bahasa barunya masih terbata-bata. Tapi setidaknya, kini ia bisa mulai menyusun kalimat. Dan yang terpenting, ada dua orang perempuan dari generasi berbeda—Mbak Surti dengan kebijakannya, dan Mbak Rara dengan komprominya—yang bersedia mendengarkan, meski dengan telinga yang berbeda.
Angin malam berhembus, menerbangkan ujung kerudung sutranya yang tergantung di jemuran. Aisyah memandang langit yang kelam dihiasi bintang-bintang yang jarang terlihat di kota. Ia menarik napas dalam, memenuhi paru-parunya dengan udara yang terasa bebas.
Ia mungkin belum menemukan jawaban final. Tapi ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga: keberanian untuk terus bertanya, dan kebebasan untuk merangkai jawabannya sendiri, satu tusuk konde, satu anyaman, satu langkah pada suatu waktu.
Bab 9: Warisan yang Dirajut
Bulan-bulan setelah pernikahan Gendhis mengalir dengan tenang, seperti sungai yang telah menemukan jalurnya setelah melewati jeram. Hubungan Aisyah dengan Mbak Rara tidak serta-merta kembali hangat seperti masa kecilnya. Kedekatan mereka sekarang lebih mirip dengan sebuah gencatan senjata yang hormat, didasari oleh pengertian diam-diam daripada kesepahaman yang utuh. Namun, ada satu perubahan penting: Mbak Rara tidak lagi menyebut kerudung Aisyah sebagai “hambatan” atau “persembunyian”. Ia menyebutnya, dengan nada yang kadang datar kadang penuh pertimbangan, sebagai “pilihan Aisyah”.
Lulusan sarjana seni rupa dengan predikat memuaskan dan instalasi RAGAM yang mendapat pujian kritis memberi Aisyah jalan baru. Ia mendapat tawaran magang di sebuah galeri seni kontemporer di Yogyakarta, sekaligus diminta untuk mengadakan workshop kecil tentang seni instalasi dan eksplorasi identitas budaya untuk komunitas remaja. Kehidupannya mulai berisi kanvas, proposal proyek, dan pertemuan dengan seniman lain.
Suatu sore, saat ia sedang menyortir bahan untuk workshopnya—kain perca, benang, kawat, foto reproduksi—telepon dari rumah keluarga besar berdering. Bukan Bunda Arum, melainkan suara Mbak Rara sendiri, yang masih terdengar resmi namun tanpa ketegangan.
“Aisyah, besok ada kegiatan di sanggar tari kecil di sini. Beberapa muridku yang masih muda akan melakukan pentas kecil. Mereka butuh bantuan merias. Kau… berminat melihat?”
Ini bukan sekadar undangan. Ini adalah tawaran untuk masuk ke dalam dunianya, bukan sebagai peserta yang dipaksa, tetapi sebagai pengamat yang diundang. Sebuah kehormatan.
“Tentu, Mbah. Aku akan datang.”
Sanggar tari itu terletak di sebuah rumah joglo yang telah dimodifikasi. Udara di dalamnya hangat oleh tubuh-t tubuh yang bergerak dan aroma minyak angin. Sejumlah remaja putri dengan wajah serius berkonsentrasi pada gerakan tangan dan lekuk leher mereka di depan cermin panjang. Mbak Rara, dengan kain jarik dan kebaya praktis, berjalan di antara mereka, membetulkan posisi jari, menegakkan postur, dengan suara yang tegas namun tidak keras.
“Nak, tolong ambilkan kotak rias di ruang belakang,” pinta Mbak Rara pada Aisyah saat melihatnya masuk.
Kotak rias itu berisi bedak, lipstik, dan peralatan dasar. Tapi di sudutnya, Aisyah melihat sesuatu yang membuatnya tersentak: beberapa buah sanggul bunting dari kayu, dan sebuah sanggul jadi yang terbuat dari rambut palsu yang disanggul rapi, siap dipakai sebagai penutup.
“Mereka masih belajar. Untuk pentas kecil, sanggul tiruan ini cukup,” jelas Mbak Rara, memperhatikan pandangan Aisyah. “Mau mencoba membantu memasangkannya?”
Aisyah tertegun. Ini bukan tentang dirinya menyanggul. Ini tentang membantu orang lain. Sebuah peran yang netral, sebuah keterampilan murni. “Aku… tidak bisa, Mbah. Aku tidak tahu caranya.”
“Aku akan mengarahkanmu,” ujar Mbak Rara, suaranya datar. “Ambil sanggul tiruan itu. Dan sisir.”
Dengan jantung berdebar, Aisyah mendekati seorang penari belia yang rambutnya telah diikat sanggul. Di bawah bimbingan singkat Mbak Rara—“Tahan rambut aslinya di sini,” “Geser sanggul tiruan dari depan ke belakang,” “Pakai jepit yang kuat di bagian samping”—Aisyah berhasil memasang sanggul tiruan itu dengan cukup rapi. Tangannya kikuk, tetapi upayanya tulus.
Saat ia selesai, penari muda itu tersenyum di cermin. “Terima kasih, Mbak.”
Kata “Mbak” itu terasa aneh sekaligus hangat. Di sini, ia bukan Aisyah si cucu pembangkang. Ia adalah “Mbak”, asisten yang membantu.
Sepanjang sore, ia membantu memasang sanggul tiruan, mengambilkan bedak, mengamati cara Mbak Rara dengan seksama. Ia melihat bagaimana neneknya tidak hanya mengajarkan gerak, tetapi juga sikap. “Tarian ini bukan soal keindahan semata,” katanya pada seorang murid yang gugup. “Ini tentang mengendalikan napas, tentang menempatkan diri dalam ruang dan waktu. Setiap gerakan adalah kata. Setiap pose adalah kalimat.”
Kalimat-kalimat itu menggema dalam diri Aisyah. Setiap gerakan adalah kata. Bukankah itu yang ia coba lakukan dengan seni instalasinya?
Pulang dari sanggar, Mbak Rara memberinya secangkir teh jahe hangat di dapur rumah keluarga. “Kau tangannya masih kaku,” ujarnya, “tapi tidak ceroboh.”
Itu adalah pujian tertinggi yang bisa Aisyah harapkan dari mulutnya.
“Mbah, tadi Mbah bilang setiap gerakan adalah kata. Apakah… menurut Mbah, karyaku bulan lalu itu juga ‘berkata’ sesuatu?”
Mbak Rara meminum tehnya, memandang keluar jendela ke arah taman. “Itu berkata banyak hal, Nak. Terlalu banyak, mungkin. Tapi satu yang aku tangkap: bahwa kau merasa terjepit, tapi kau masih berusaha mencari kata-kata dari dalam tekanan itu.” Ia menoleh ke Aisyah. “Mungkin itu juga sebuah bentuk ketegangan. Seperti gerakan patrap dalam tari, tubuh tegang tetapi penuh tenaga yang tertahan, menunggu untuk dilepaskan.”
Analogi itu membuat Aisyah tercengang. Neneknya melihat karyanya melalui lensa yang ia pahami: tarian. Dan dalam bahasa itu, ia menemukan titik temu.
“Aku sedang mempersiapkan proyek baru, Mbah,” ungkap Aisyah, tiba-tiba berani. “Tentang warisan perempuan, tentang benda-benda yang diwariskan. Bukan hanya fisik, tapi juga… gerak, nasihat, rasa sakit, harapan. Aku ingin… bolehkah aku mewawancarai Mbah? Bukan sebagai cucu, tapi sebagai seniman.”
Mbak Rara terdiam lama. Kemudian, dengan sangat pelan, ia mengangguk. “Boleh. Tapi jangan pakai alat perekam suara yang besar-besar. Bikin aku gugup.”
Proyek baru Aisyah berjudul “Benang Pengikat Waktu”. Ia mengumpulkan cerita dari perempuan-perempuan di keluarganya dan komunitas sekitarnya. Dari Bunda Arum, ia mendapat cerita tentang tekanan menjadi anak seorang penjaga tradisi dan pilihan menikah dengan orang “biasa”. Dari seorang tantenya, ia mendapat kisah tentang memilih karier di luar rumah di era yang berbeda. Dan dari Mbak Rara, dalam beberapa sesi wawancara singkat di teras rumah, ia mendapat cerita-cerita yang jauh lebih dalam dari sekadar tari.
Ia bercerita tentang rasa takut saat pertama kali menari di depan publik, tentang bangga ketika dipuji, tentang sedih ketika tradisi mulai ditinggalkan, tentang tekadnya untuk meneruskan apa yang ia tahu meski dunia berubah. “Warisan itu seperti tanaman, Nak,” kata Mbak Rara suatu sore. “Kau tidak bisa hanya memetik bunganya dan membuang akarnya. Tapi kau juga tidak bisa memaksanya tumbuh di pot yang sama selamanya. Kadang, ia butuh dipindah, dikasih tanah baru, agar tetap hidup.”
Aisyah mencatat setiap kata. Ia mulai mengumpulkan benda-benda: sapu tangan lama Mbak Rara, potongan kain dari kebaya yang sudah usang, foto-foto, bahkan butiran-butiran melati kering yang masih menyimpan aroma samar. Ia juga menggunakan kembali material dari instalasi RAGAM, mendaur ulangnya menjadi sesuatu yang baru.
Karya barinya tidak lagi berupa torso yang terisolasi. Ia menciptakan sebuah ruang instalasi yang lebih luas: dari langit-langit, ia gantungkan banyak “akar” dari benang-benang warna berbeda yang terjalin—ada benang emas (tradisi istana), benang merah (keberanian), benang putih (kesucian niat), benang hitam (kesedihan dan tekanan). Akar-akar benang itu menjuntai ke bawah, menyentuh berbagai “benda tanah”: sanggul tiruan yang retak, kerudung sutra yang terbuka seperti kuncup, buku catatan tua yang terkulai, dan di tengah-tengahnya, sebuah cermin bulat yang memantulkan wajah siapa pun yang berdiri di depannya.
Di dinding, ia memproyeksikan video montase: cuplikan gerakan tari tangan Mbak Rara yang lambat, diselingi dengan cuplikan video dirinya merangkai kain, dan tangan-tangan perempuan lain dalam keluarganya yang sedang melakukan aktivitas sehari-hari—memasak, menulis, memegang anak.
Ia tidak lagi sekadar berbicara tentang konfliknya sendiri. Ia berbicara tentang continuum, tentang rantai panjang perempuan yang masing-masing merajut makna dari benang warisan yang mereka terima, dengan pola yang berbeda-beda.
Pada malam pembukaan pameran proyek ini, di sebuah galeri alternatif yang lebih kecil namun penuh dengan komunitas, Mbak Rara datang lagi. Kali ini, ia datang dengan beberapa murid tarinya. Mereka berjalan pelan di ruangan, melihat akar-akar benang yang terjalin, mendengar rekaman suara perempuan-perempuan bercerita yang diputar dengan volume pelan.
Mbak Rara berhenti lama di depan cermin bulat di tengah ruangan. Ia melihat pantulan dirinya yang sudah tua, tercampur dengan pantulan akar-akar benang di belakangnya, seolah-olah ia sendiri adalah bagian dari tanaman raksasa itu. Lalu, ia melihat Aisyah yang sedang berdiri di seberang ruangan, memandangnya.
Nenek itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangkat tangan kanannya, perlahan, melakukan gerakan dasar tari Jawa: ukel, gerakan memutar pergelangan tangan yang lembut namun penuh kesadaran. Gerakan itu sederhana, tetapi dalam konteks ruang instalasi itu, terasa seperti sebuah salam. Sebuah pengakuan. Sebuah cara berkata “aku melihat benangmu. Dan aku mengakui benangku ada di dalam anyaman itu.”
Aisyah, dengan mata berkaca-kaca, membalas dengan gerakan yang sama: ukel. Dari jarak beberapa meter, di tengah karya seni yang lahir dari pergulatan mereka, dua perempuan dari generasi yang berbeda itu saling menyapa dalam bahasa yang akhirnya mulai mereka pahami bersama: bahasa gerak, bahasa bentuk, bahasa warisan yang terus-menerus dirajut ulang.
Proyek “Benang Pengikat Waktu” tidak menyelesaikan semua perbedaan. Masih akan ada salah paham, masih akan ada keheningan yang canggung di keluarga besar. Tapi malam itu, Aisyah menyadari sesuatu. Resolusi bukanlah tentang menemukan titik temu di mana semua setuju. Resolusi adalah tentang menciptakan ruang yang cukup luas sehingga perbedaan bisa berdiri berdampingan, saling mengakui kehadirannya, dan bahkan—dalam momen-momen tertentu—bisa saling menyapa.
Ia memegang tusuk konde perak pemberian Mbak Rara dan tusuk konde kayu pemberian Mbah Surti, yang kini selalu ia simpan di tas kerjanya. Dua benda dari dua dunia yang kini menjadi kompasnya. Bukan untuk menunjukkan jalan yang lurus, tetapi untuk mengingatkannya bahwa jalan itu bisa berliku, bisa bercabang, dan bahwa keindahan seringkali terletak pada kemampuan untuk merangkai setiap liku dan cabang itu menjadi sebuah pola yang berarti.
Perjalanannya masih panjang. Tapi kini, ia berjalan dengan sebuah keyakinan baru: bahwa warisan bukanlah beban mati yang harus dipikul, melainkan benang hidup yang harus dirajut. Dan ia, dengan segala kebingungan, keberanian, dan kekakuan tangannya, adalah perajut generasinya.
Bab 10: Mahkota yang Tumbuh
Lima tahun bukanlah waktu yang singkat. Cukup untuk mengubah seorang lulusan sarjana yang penuh tanya menjadi seorang seniman dengan nama yang mulai dikenal di lingkupnya. Cukup untuk mengubah hubungan yang retak menjadi sebuah pola baru yang lebih kuat, meski masih tetap memiliki garis-garis yang menandai bekas penyambungannya.
Studio Aisyah sekarang menempati sebuah ruang lebih luas di lantai dua sebuah rumah tua yang direnovasi di kawasan Prawirotaman. Sinar matahari pagi menerpa meja kerjanya yang masih berantakan dengan proyek-proyek yang sedang berjalan: sketsa untuk instalasi publik, contoh kain, dan di tengah-tengahnya, sebuah undangan mewah.
Undangan untuk peluncuran buku dan pameran retrospeksi kecil karya-karyanya selama lima tahun terakhir, di sebuah galeri ternama. Di sampul undangan, terdapat gambar detail dari instalasi terbarunya: sebuah mahkota besar yang terbuat dari anyaman akar wangi, benang sutra, dan serpihan keramik tua, yang bentuknya mengingatkan pada sanggul namun juga pada kubah. Judulnya: “Mahkota yang Tumbuh dari Leher yang Sama.”
Namun, di antara kesibukan mempersiapkan pameran penting itu, ada satu hal yang lebih mendesak di pikirannya. Di atas meja, di samping undangan, terbaring sebuah paket sederhana dibungkus kertas coklat. Isinya: sebuah kebaya kain sutra natural yang sangat halus, dengan hiasan sulam bayangan berwarna senada yang nyaris tak terlihat, elegan dan tidak mencolok. Kebaya ini dikirimkan oleh Mbak Rara, dengan pesan singkat dari Bunda Arum: “Dikirim khusus untuk acara pameranmu. Kata Mbah, biar sesuai dengan ‘bahasamu’ sekarang.”
Aisyah menyentuh kain sutra yang dingin itu. Ini bukan kebaya upacara adat lengkap. Ini adalah kebaya modern yang dijahit dengan pola tradisional. Sebuah adaptasi. Sebuah penerimaan. Air matanya menitik, membasahi bungkus kertas. Perjalanan panjang dari penolakan, melalui konflik berdarah-darah, kompromi yang canggung, hingga kini sampai pada titik di mana neneknya justru mengirimkan busana yang mendukung ‘bahasa’ barunya.
Pameran retrospeksi itu sendiri adalah sebuah perjalanan visual melalui pergulatan identitasnya. Ruang galeri dibagi menjadi beberapa zona. Zona pertama menampilkan foto dokumentasi “RAGAM: Dari Leher yang Sama”, karya yang memicu segala sesuatu. Di sebelahnya, ada video “Merangkai Diatas Diri” yang diputar dalam monitor kecil, seperti sebuah permulaan yang intim.
Zona kedua adalah “Benang Pengikat Waktu”, instalasi yang lebih kompleks tentang warisan perempuan. Zona ketiga menampilkan karya-karya transisi: eksperimen dengan bentuk-bentuk sanggul dari material daur ulang, cetakan tubuh dengan pola kaligrafi dan motif batik yang menyatu.
Dan di ruang utama, berdiri instalasi terbarunya, “Mahkota yang Tumbuh dari Leher yang Sama”. Mahkota itu tidak dipajang di atas torso atau maneken. Ia menggantung di udara, setinggi kepala manusia, terhubung dengan langit-langit oleh ratusan benang transparan yang hampir tak terlihat, sehingga seolah-olah melayang. Dari bawah, pengunjung bisa berjalan masuk ke bawahnya, dan melihat ke atas: anyaman akar wangi, sutra, dan keramik itu membentuk sebuah kanopi yang rumit dan indah, yang memfilter cahaya menjadi pola-pola yang menari di lantai. Di bagian dalam mahkota, terselip dengan rapi, terlihat secarik kain kerudung sutra krem yang telah usang namun dicuci bersih—kain dari kerudung yang ia pakai pada video performatif pertamanya dulu. Ia menyatukan titik awal dan titik sekarang.
Malam pembukaan ramai. Dunia seni Yogyakarta datang, bersama koleganya, mantan dosen, dan keluarga. Aisyah, dengan jantung berdebar, berdiri di samping mahkota raksasanya. Ia mengenakan kebaya sutra pemberian Mbak Rara, dipadukan dengan kain panjang tenun modern. Dan di kepalanya, ia tidak mengenakan sanggul, juga tidak mengenakan kerudung yang ia pakai sehari-hari. Sebagai gantinya, rambutnya yang telah panjang diatur dalam konde rendah yang sederhana dan rapi, dihiasi dengan dua tusuk konde: yang kayu cendana di sisi kiri, yang perak bermata kecubung di sisi kanan. Sehelai syal sutra tipis berwarna sama dengan kebaya dililitkan longgar di sekitar pundak dan lehernya, bisa dibaca sebagai aksesori, bisa dibaca sebagai kerudung yang sangat longgar, bisa dibaca sebagai apa saja. Ia telah menemukan estetika personalnya: elemen dari kedua dunia, disusun dengan caranya sendiri, tidak lagi sebagai pertentangan, tetapi sebagai perpaduan yang disengaja.
Lalu, ia melihat mereka masuk.
Mbak Rara, dengan didampingi Bunda Arum dan ayah Aisyah, melangkah masuk ke galeri. Nenek itu terlihat lebih ringkih, berjalan dengan tongkat, tetapi masih dengan postur tegak dan tatapan yang tajam. Ia memakai kebaya sederhana, tapi Aisyah memperhatikan sesuatu yang baru: di sanggul gelung tekuk putihnya yang rapi, tertancap sebuah tusuk konde baru—sebuah replika sederhana dari tusuk konde kayu cendana, terbuat dari perak. Sebuah penghormatan balik.
Mbak Rara tidak terburu-buru. Ia menyusuri setiap zona dengan perlahan, seperti seorang kurator. Di depan foto-foto instalasi RAGAM, ia berhenti lama. Di depan video Merangkai Diatas Diri, ia mengangguk pelan. Saat tiba di ruang utama dan melihat mahkota yang melayang, ia terdiam. Matanya, dari balik kacamata baca, memandang ke atas, menyelami setiap anyaman, setiap pola cahaya.
Aisyah mendekat, tidak yakin harus berkata apa.
Mbak Rara menoleh padanya. Di kerutan di sudut matanya, ada sesuatu yang lembut. “Jadi ini… mahkotamu yang sudah tumbuh?”
Suara Aisyah tersekat. “Iya, Mbah. Ia tumbuh dari… dari semua itu.” Ia menunjuk ke zona-zona sebelumnya.
Mbak Rara mengangkat tangannya, bukan untuk menyentuh mahkota, tetapi untuk menunjuk ke arah kain kerudung usang yang terselip di dalam anyaman. “Itu yang dulu?”
“Iya.”
“Kau simpan baik-baik.”
“Selalu, Mbah.”
Mbak Rara memandangnya sekilas, lalu kembali ke mahkota. “Indah. Rumit. Seperti hidup.” Ia berhenti, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih rendah, hanya untuk Aisyah. “Dulu aku ingin kau memakai mahkota yang sudah jadi, yang polanya sudah kutetapkan. Aku khawatir jika kau membuat mahkotamu sendiri, hasilnya akan berantakan.” Ia menarik napas. “Ternyata, aku salah. Mahkota buatanmu… lebih kuat. Karena kau yang merajut setiap simpulnya. Kau yang tahu makna setiap helai benangnya.”
Itu adalah pengakuan terdalam, paling jelas, yang pernah Aisyah dengar. Ia menggenggam tangan neneknya yang ringkih. “Terima kasih, Mbah. Terima kasih sudah memberiku benangnya.”
Malam itu berlanjut dengan pujian, diskusi seni, dan champagne. Tapi momen paling berharga bagi Aisyah terjadi di akhir acara, saat hampir semua orang sudah pulang. Ia dan Mbak Rara duduk di bangku di teras galeri, melihat lalu lintas malam.
“Aku sudah tua, Aisyah,” ucap Mbak Rara tiba-tiba. “Tidak akan lama lagi aku meninggalkan dunia yang penuh dengan aturan dan keanggunan yang kukenal ini.”
“Jangan berkata begitu, Mbah.”
“Tenang. Ini bukan keluhan. Ini adalah… penerusan.” Mbak Rara membuka tas kecilnya, mengeluarkan sebuah buku catatan kulit yang tipis dan usang. “Ini. Catatan tentang tari, tentang filosofi gerak, tentang makna di balik sanggul dan busana yang tidak sempat aku tulis dengan rapi. Mungkin bahasanya kuno. Tapi isinya… isinya adalah benang-benang dari mahkotaku.” Ia menyerahkan buku itu ke tangan Aisyah. “Jagalah. Dan jika mau, tambahkan benang-benangmu di dalamnya. Supaya mahkota kita tidak berhenti tumbuh.”
Aisyah menerima buku itu seperti menerima sebuah pusaka. Lebih berharga dari tusuk konde perak mana pun. Ini adalah inti dari warisan Mbak Rara: bukan bendanya, tetapi pengetahuannya, filosofinya.
“Aku akan menjaganya, Mbah. Aku janji.”
Mbak Rara menganggak, lalu menatap langit malam yang berpolusi cahaya kota. “Kau tahu, dulu aku marah karena kau sepertinya menolak untuk menjadi seperti aku. Tapi sekarang aku melihat… mungkin tugas seorang nenek bukanlah untuk menghasilkan cucu yang serupa. Tapi untuk memastikan bahwa apa pun yang jadi pilihan cucunya, ia melakukannya dengan kesadaran, dengan keanggunan dari dalam, dan dengan rasa hormat pada benang yang menghubungkannya dengan masa lalu.” Ia menepuk tangan Aisyah. “Kau sudah menemukan keanggunanmu sendiri. Itu yang terpenting.”
Keesokan harinya, Aisyah duduk di studionya, buku catatan Mbak Rara terbuka di pangkuannya. Di halaman pertama, tulisan tangan yang rapi berbunyi: “Gerakan pertama bukanlah kaki. Ia adalah napas. Mengenal diri sendiri dimulai dari menyadari napas yang masuk dan keluar…”
Ia tersenyum. Ia mengambil buku sketsanya yang baru, dan di halaman pertama, ia mulai menulis:
“Proyek Baru: ‘Napas dan Anyaman’
Menggabungkan filosofi gerak tari Jawa (warisan Mbak Rara) dengan proses penciptaan seni instalasi (jalanku). Mungkin dalam bentuk pertunjukan interdisipliner. Penari dan perajut. Gerak dan benang. Napas yang sama…”
Di luar jendela, cahaya matahari menerpa tusuk konde perak dan kayu yang tergeletak di meja, memantulkan kilauan kecil. Dua benda dari dua dunia yang berbeda, kini diam berdampingan dengan damai, menjadi saksi bisu dari sebuah perjalanan panjang dari penolakan, melalui konflik yang menyakitkan, menuju pengertian, dan akhirnya, menuju penciptaan bersama.
Aisyah memandang kota di balik jendela. Ia tidak lagi melihat dikotomi. Ia melihat sebuah kanvas luas yang penuh dengan kemungkinan anyaman. Kerudung di tengah geliat budaya sanggul bukan lagi sebuah pertentangan, melainkan sebuah benang dalam tenun yang lebih besar. Dan ia, dengan semua kompleksitasnya, adalah sekaligus benang, alat tenun, dan penenunnya.
Perjalanannya belum selesai. Tapi kini, ia berjalan tidak dengan beban dua dunia di pundaknya, melainkan dengan dua benang di tangannya—siap untuk dirajut, dipelintir, atau ditinggalkan longgar, menjadi bagian dari pola yang terus bertumbuh, seluas dan serumit kehidupan itu sendiri. Mahkotanya bukan lagi benda yang harus dipakai atau ditanggalkan. Ia adalah proses yang hidup. Dan itulah warisan sejati yang ia temukan: kebebasan untuk tumbuh, dengan akar yang tahu dari mana asalnya.
Bab 11: Simfoni Seribu Benang
Tiga tahun berlalu sejak pameran retrospeksi. Buku catatan Mbak Rara telah menjadi sumber air yang tak habis-habisnya bagi Aisyah. Ia tidak hanya membacanya; ia menghidupkannya dalam karya-karyanya yang semakin matang. Kolaborasinya dengan penari, musisi tradisional, dan perajut komunitas melahirkan sebuah genre seni pertunjukan baru yang ia sebut “Seni Titis”—seni yang menitikberatkan pada aliran, kesinambungan, dan transformasi warisan.
Namun, waktu juga yang tak kenal kompromi. Usia dan penyakit perlahan-lahan merenggut keteguhan Mbak Rara. Setelah dirawat di rumah sakit akibat komplikasi ringan, sang penari legendaris itu memutuskan untuk menghabiskan sisa waktunya di rumah, dikelilingi benda-benda dan kenangan seumur hidupnya.
Suatu sore yang tenang, Aisyah duduk di samping tempat tidur neneknya. Kamar itu beraroma campuran minyak angin, bunga melati segar dalam vas, dan obat-obatan. Sinar matahari sore menyelinap melalui jendela, menerpa wajah Mbak Rara yang terlihat lebih kecil di antara bantal-bantal.
“Aisyah,” panggil Mbak Rara dengan suara yang tipis namun masih jelas. Matanya yang mulai kabur mencari wajah cucunya.
“Iya, Mbah. Aku di sini.”
“Bawa kemari… kotak kayu di lemari itu.”
Aisyah mengambil kotak kayu jati tua yang ia kenal—kotak yang sama dulu digunakan Mbak Rara untuk menyimpan tusuk konde pemberiannya. Dengan tangan gemetar, Mbak Rara membukanya. Di dalamnya, tidak hanya ada perhiasan. Ada surat-surat tua, potongan koran, dan sebuah bundel kain mori putih yang diikat benang emas.
“Ini… untukmu,” ujar Mbak Rara, mengeluarkan bundel itu. “Buka.”
Dengan hati-hati, Aisyah membuka ikatannya. Yang terbentang adalah sehelai kemben—kain penutup dada penari tradisional—dari kain primis putih yang sudah menguning. Di atas kain itu, dengan tinta coklat yang memudar, tertera puluhan bahkan mungkin ratusan tanda tangan, cap jempol, dan coretan nama dalam aksara Jawa dan Latin.
“Ini adalah…?” tanya Aisyah, takjub.
“Kemben kenanganku,” jawab Mbak Rara, matanya berbinar dengan cahaya kenangan. “Setiap kali aku mengajar, setiap kali ada murid yang pentas pertama kali, atau setiap kali ada peristiwa penting di sanggarku… aku minta mereka meninggalkan tanda di sini. Murid-muridku, dari yang sekarang sudah nenek-nenek sampai yang masih kecil. Teman-teman seperjuangan. Ini… adalah jejak mereka. Jejak bahwa apa yang kulakukan… bersambung.”
Aisyah menelusuri setiap tanda dengan ujung jarinya. Ia bisa merasakan getaran sejarah di kain itu. Sebuah warisan yang bukan benda mati, tetapi jejak hidup.
“Aku tidak memberimu pusaka yang mahal,” lanjut Mbak Rara. “Aku memberimu… bukti bahwa warisan itu hanya berarti jika dihidupi. Dan cara menghidupinya… bisa beragam.” Ia menarik napas berat. “Jahitlah kain ini… ke dalam mahkotamu yang berikutnya. Biar mereka… semua orang yang pernah kusentuh… juga menjadi bagian dari anyamanmu.”
Air mata Aisyah jatuh menetes di atas kemben tua itu. Ini adalah warisan terakhir yang paling menghancurkan sekaligus paling membangun. “Aku tidak akan menyia-nyiakannya, Mbah. Aku janji.”
Mbak Rara tersenyum lemah, mengangkat tangan keriputnya untuk menyentuh pipi Aisyah. “Aku tahu. Karena kau… sudah menemukan nadamu sendiri dalam simfoni yang panjang ini.” Tangannya jatuh lemas. “Kini… biarkan Mbah istirahat.”
Minggu-minggu berikutnya adalah masa-masa peralihan. Aisyah menghabiskan hampir setiap hari di rumah keluarga besar, menemani, membacakan buku, atau sekadar duduk dalam keheningan bersama Mbak Rara. Dalam keheningan itu, tidak ada lagi kata-kata yang perlu diperjuangkan. Hanya ada kehadiran, sebuah bahasa yang lebih dalam dari semua dikotomi.
Saat akhir itu tiba, ia datang dengan tenang dalam tidur. Dunia kehilangan seorang penjaga tradisi yang teguh. Keluarga besar kehilangan porosnya. Dan Aisyah kehilangan seorang nenek, seorang musuh, seorang penentang, seorang guru, dan akhirnya, seorang sekutu.
Dalam kesedihan yang mendalam, ada juga sebuah kelegaan. Tidak ada kata-kata yang tersisa tak terucapkan. Tidak ada penyesalan yang menganga. Hanya ada sebuah kain kemben bertanda tangan yang terbentang di studio Aisyah, menunggu untuk dirajut ke dalam kehidupan baru.
Proses berduka Aisyah tidak dengan duduk diam. Ia melakukannya dengan cara yang ia kenal: mencipta. Kemben bertanda tangan itu menjadi jantung dari proyek barunya, yang ia beri judul “Simfoni Seribu Benang: Nyanyian untuk Seorang Penari.”
Ia tidak membuat instalasi statis. Ia menciptakan sebuah pertunjukan instalasi yang melibatkan banyak orang. Ia mengundang semua murid Mbak Rara yang bisa ia hubungi, dari berbagai generasi. Ia juga mengundang para perajut dari komunitasnya, serta pemusik tradisional.
Panggungnya kosong. Hanya dari langit-langit, tergantung kemben bertanda tangan itu, dipajang seperti sebuah bendera suci yang transparan. Di bawahnya, tersebar gulungan benang dalam berbagai warna dan material—benang emas, sutra, katun, bahkan benang dari plastik daur ulang.
Saat pertunjukan dimulai, lampu menyorot kemben. Seorang penari tua, murid pertama Mbak Rara, masuk. Dengan gerakan lambat dan penuh hormat, ia mengambil seutas benang emas, mengikatkan salah satu ujungnya ke pinggir kemben, lalu menarik benang itu ke bawah, dan mulai menari. Setiap gerakannya memelintir, menganyam benang itu di udara dan di lantai, menciptakan pola.
Kemudian, penari lain masuk, dari generasi berbeda. Ia mengambil benang sutra warna krem—warna kerudung Aisyah—dan melakukan hal yang sama, menambahkan lapisan anyaman baru. Satu per satu, perempuan-perempuan dari berbagai usia masuk, masing-masing memilih benang yang mewakili mereka (ada yang warna hijau daun, biru langit, merah marun), dan menari, merajut benang mereka ke dalam jaringan yang semakin kompleks di bawah kemben.
Aisyah sendiri tidak menari. Ia duduk di sisi panggung, dengan sebuah alat tenun kecil portabel. Dari benang-benang yang telah ditarik dan ditenun di udara oleh para penari, ia dengan sabar memunguti ujung-ujungnya, dan mulai merajutnya di alat tenunnya, menciptakan sebuah kain panjang yang baru. Di kain baru itu, terselip potongan-potongan kecil dari kerudung lamanya, dari kain kebaya pemberian Mbak Rara, dan dari serpihan sanggul tiruan.
Musik gamelan dimainkan hidup, mengikuti irama gerakan para penari dan hentakan alat tenun Aisyah. Suara desahan napas, gesekan benang, dan dentingan gamelan menyatu menjadi sebuah simfoni yang menghanyutkan.
Puncak pertunjukan terjadi saat semua penari telah masuk. Jaringan benang di bawah kemben telah menjadi hutan yang rumit dan indah. Lalu, mereka berhenti. Dalam keheningan yang tiba-tiba, seorang pemusik memainkan suling dengan nada melankolis yang merdu.
Aisyah berdiri, membawa kain panjang yang telah ia rajut. Dengan bantuan para penari, ia mengangkat kain itu, dan dengan gerakan yang sangat hati-hati, mereka menyampirkannya ke jaringan benang yang ada, menambahkan lapisan terakhir. Kain baru itu menutupi sebagian jaringan, menyatukan semua benang yang beraneka warna menjadi sebuah kesatuan visual yang utuh.
Lampu kemudian berpindah, hanya menyinari kemben bertanda tangan di atas, yang kini terhubung dengan jaringan benang dan kain baru di bawahnya oleh ribuan benang vertikal. Ia seperti sebuah matahari, sebuah sumber, yang memancarkan sinarnya dalam bentuk benang-benang kehidupan yang kemudian ditenun menjadi sebuah tapestri raksasa oleh tangan-tangan banyak perempuan dari berbagai zaman.
Tepuk tangan menggema. Banyak yang menangis, terutama para murid Mbak Rara yang hadir. Mereka melihat guru mereka dihormati bukan dengan patung atau pidato, tetapi dengan sebuah metafora hidup tentang sambung-menyambung, tentang warisan yang terus mengalir dan berubah bentuk.
Setelah pertunjukan, seorang murid Mbak Rara yang sudah sepuh mendekati Aisyah. Matanya basah.
“Dulu, Mbak Rara sering khawatir garisnya akan putus,” ujarnya. “Tapi malam ini… aku melihat garisnya tidak putus. Hanya berbelok, bercabang, dan menjadi… sesuatu yang lebih luas.”
Itulah esensinya. Warisan bukan garis lurus. Ia adalah anyaman. Dan dalam anyaman, setiap benang, meski berbeda warna dan kekuatan, punya tempat. Benang yang kaku seperti keyakinan Mbak Rara pada tradisi. Benang yang fleksibel seperti pencarian spiritual Aisyah. Benang-benang tipis dari murid-murid yang lain. Semua diperlukan untuk menciptakan kekuatan dan keindahan kain tersebut.
Kemben bertanda tangan itu kemudian ia bingkai dengan kaca, tapi tidak dipajang di dinding seperti benda mati. Ia digantung di studionya dengan benang-benang yang terjuntai ke bawah, dan siapa pun yang datang—murid workshopnya, kolega seniman—diundang untuk mengambil seutas benang baru, mengikatkannya ke salah satu benang yang terjuntai itu, dan menceritakan singkat tentang warisan perempuan dalam hidup mereka. Kemben itu menjadi sebuah karya yang terus tumbuh, sebuah instalasi hidup yang menjadi testimoni tentang sambung-menyambung.
Suatu hari, saat membersihkan studio, Aisyah menemukan kembali tusuk konde kayu dan perak yang sempat terlupakan di antara tumpukan material. Ia memegangnya, merasakan kembali berat dan sejarahnya. Lalu, dengan sebuah ide, ia menggantung kedua tusuk konde itu di antara benang-benang yang terjuntai dari kemben, seolah-olah mereka adalah dua titik penting dalam anyaman yang besar.
Dia melihat ke cermin di studionya. Perempuan yang memandang balik padanya tidak lagi gadis yang bingung atau pemuda yang memberontak. Dia adalah seorang wanita dengan mata yang tenang, dengan garis-garis kecil di sudut matanya yang bercerita tentang perjalanan. Di kepalanya, tidak ada sanggul megah atau kerudung ketat. Rambutnya diikat longgar, dan di sekeliling lehernya, ia melilitkan syal sutra yang dulu menjadi bagian dari “bahasa barunya”—sekarang sudah menjadi bagian alih dari sehari-harinya.
Kerudung di tengah geliat budaya sanggul. Itu dulu adalah masalah, sebuah dikotomi yang menyakitkan. Kini, itu hanyalah salah satu pola dalam tenun yang lebih besar. Sebuah pola yang indah karena kontrasnya, karena cerita yang dibawanya.
Aisyah mengambil buku catatan Mbak Rara yang sudah mulai lusuk, dan buku sketsanya yang penuh dengan ide-ide baru. Ia membuka halaman kosong, dan mulai menulis:
“Proyek Komunitas: Sekolah Anyaman. Mengajarkan seni merajut tidak hanya dengan benang, tetapi dengan cerita. Setiap peserta membawa sepotong kain atau benda yang bermakna, dan bersama-sama kita merajutnya menjadi sebuah karya kolosal. Memulainya dengan bertanya: ‘Benang apa yang kamu bawa hari ini?’”
Dia meletakkan pulpennya, memandang keluar jendela. Kota Yogya yang selalu berubah, memegang tradisi dengan satu tangan dan merangkul modernitas dengan tangan lainnya. Seperti dirinya.
Perjalanannya dari konflik ke kreasi mungkin adalah warisan terbesarnya. Dan warisan itu, ia sadari, bukan untuk disimpan sendiri. Ia untuk dibagikan, untuk menginspirasi orang lain yang mungkin juga merasa terjepit di antara berbagai identitas.
Dengan kedua tusuk konde bergantung di belakangnya, dan kain kemben penuh tanda tangan berdenyut di tengah studionya, Aisyah tersenyum. Dia tidak lagi mencari satu mahkota yang pas. Karena dia telah memahami bahwa dirinya sendiri—dengan semua kompleksitas, pertanyaan, dan upaya merajutnya—adalah mahkota yang terus bertumbuh. Dan pertumbuhan itu, dengan segala liku dan keindahannya, adalah sebuah simfoni yang tak pernah benar-benar berakhir.
Bab 12: Warisan yang Bernapas
Tujuh tahun kemudian.
Udara di Bandara Internasional Yogyakarta terasa lembab dan ramai. Aisyah, kini di pertengahan tiga puluhan, berdiri di balik pembatas kedatangan dengan jantung berdebar kencang berbeda. Di tangannya, ia memegang seikat bunga melati dan sebuah buku kecil terbungkus kain. Di sebelahnya, Rendra—kini seorang sutradara teater yang cukup terkenal—berdiri dengan tenang, sesekali melirik jam tangan.
“Dia pasti sudah besar,” gumam Aisyah, merapikan syal sutra di lehernya yang hari ini dipadukan dengan tunik linen dan celana panjang yang lapang.
“Dan kau pasti akan langsung mengenalinya,” jawab Rendra sambil tersenyum. “Darah senimu pasti mengalir deras padanya.”
Kedatangan yang mereka tunggu adalah Alika, keponakan sepupu jauh yang baru berusia sembilan belas tahun. Putri dari sepupu yang tinggal di Amsterdam, Alika memilih untuk melanjutkan studi seni rupa di Indonesia, dan lebih spesifik lagi, magang di studio Aisyah. Dari beberapa percakapan daring, Aisyah menangkap kegelisahan yang akrab: seorang perempuan muda keturunan Jawa yang tumbuh di Barat, dengan rambut ikal alami yang sulit diatur, yang merasa terombang-ambing antara ingin memahami akarnya dan menolak stereotip yang dibebankan padanya. Dalam sebuah email, Alika pernah menulis: “Tante, aku bingung. Di sini aku selalu ‘si gadis eksotis’. Aku ingin datang ke sumbernya, tapi takut hanya akan jadi turis di tanah leluhur sendiri.”
Pintu kedatangan terbuka. Arus penumpang mulai mengalir. Dan kemudian, Aisyah melihatnya. Seorang gadis tinggi dengan postur tegap, rambut ikal hitamnya dibiarkan tergerai bebas. Dia mengenakan hoodie oversized dan celana jeans sobek, sebuah ransel besar di punggungnya. Matanya—mata yang mirip dengan garis keluarga—berkeliaran, mencari-cari dengan campuran antisipasi dan kecemasan.
Saat pandangan mereka bertemu, Aisyah mengangkat sedikit buku yang ia pegang. Gadis itu tersenyum lega dan berjalan mendekat.
“Alika?” tanya Aisyah.
“Tante Aisyah?” balas Alika, suaranya terdengar lebih muda dari yang dibayangkan.
Mereka berpelukan ringan. “Selamat datang di rumah,” sambut Aisyah.
“Ini Om Rendra,” perkenalkan Aisyah. Rendra menyambut dengan senyum khasnya.
Dalam perjalanan ke studio, Alika tak henti-hentinya memandang keluar jendela, menyerap pemandangan Yogya yang hiruk-pikuk dan penuh kontras. “Sangat berbeda,” gumamnya. “Tapi… terasa seperti sesuatu menarik-narik di sini,” katanya sambil menepuk dadanya.
Studio Aisyah telah berkembang menjadi lebih dari sekadar tempat kerja. Ia adalah sebuah ruang komunitas kecil. Satu sisi adalah area kerja dengan meja panjang, rak material, dan karya-karya dalam proses. Sisi lainnya adalah ruang pertemuan dengan bantal-bantal lesehan dan rak buku. Di dinding utama, terpajang dengan bangga adalah Kemben Bertanda Tangan Mbak Rara, yang kini telah menjadi titik pusat dari sebuah instalasi hidup yang jauh lebih besar. Dari kemben itu, menjuntai ratusan—bahkan mungkin ribuan—utas benang dalam berbagai warna dan ketebalan. Masing-masing benang diikatkan pada gulungan kecil yang berisi cerita singkat tentang perempuan yang menambahkannya. Beberapa benang terjulur hingga ke lantai, menyatu dengan permadani rajutan besar yang juga merupakan karya kolaboratif.
Alika terpana saat masuk. Matanya membulat. “Ini… ini luar biasa,” bisiknya, mendongak melihat hujan benang yang menggantung dari langit-langit. “Ini seperti… hutan cerita.”
“Itulah tepatnya,” jawab Aisyah. “Setiap benang adalah sebuah suara. Sebuah warisan.”
Alika berjalan mendekati dinding, membaca beberapa gulungan cerita yang tergantung. “Nenekku… Mbak Rara. Dia yang memulai ini?” tanyanya, melihat foto kecil Mbak Rara yang dipajang di samping kemben.
“Iya. Dia yang memberiku benang pertama.” Aisyah menunjuk tusuk konde kayu dan perak yang tergantung di dekatnya. “Dan itu dua pemberiannya.”
Sepanjang minggu pertama, Alika mengamati. Ia melihat bagaimana Aisyah bekerja: merancang instalasi untuk pameran, memimpin workshop “Sekolah Anyaman” untuk remaja putri, berdiskusi dengan penari untuk kolaborasi berikutnya. Ia melihat bagaimana Aisyah dengan mudah bergerak antara dunia tradisi dan kontemporer, tidak dengan sikap mengalahkan yang satu untuk yang lain, tetapi dengan menghormati keduanya.
Suatu sore, saat mereka berdua sedang membersihkan studio, Alika akhirnya menyuarakan kegelisahannya.
“Tante, aku merasa seperti penipu,” akunya, menyeka debu dari sebuah patung torso tua. “Aku datang ke sini untuk ‘mencari akar’, tapi apa yang aku tahu? Aku tidak bisa menari. Aku tidak bisa bahasa Jawa halus. Rambutku bahkan tidak lurus untuk disanggul.” Ia meraih rambut ikalnya yang berantakan. “Aku cuma bisa bikin seni kontemporer yang mungkin dianggap ‘tidak Jawa’ oleh keluarga sini, dan ‘terlalu etnis’ oleh orang Eropa.”
Aisyah berhenti menyapu, dan duduk di sebelah Alika. Ia mendengar gema dari masa lalunya sendiri dalam suara keponakannya.
“Alika, lihat ini.” Aisyah menunjuk ke instalasi benang raksasa di dinding. “Apa yang kau lihat?”
“Banyak benang. Banyak warna. Terlihat agak… berantakan tapi teratur.”
“Benar. Tidak ada satu benang di sini yang sama. Ada yang dari sutra halus warisan penari. Ada yang dari benang katun biasa seorang ibu rumah tangga. Ada yang dari kawat daur ulang seorang seniman muda. Bahkan ada benang dari plastik bekas yang dibawa seorang aktivis lingkungan.” Aisyah memandang Alika. “Akar itu bukan tentang menjadi sama dengan nenek moyangmu. Akar adalah tentang memahami dari bahan apa kau dibuat. Dan kau, Alika, terbuat dari bahan yang berbeda dari Mbak Rara, juga berbeda dariku. Kau punya benang Eropa yang kuat, benang Jawa yang mungkin masih kusut, dan benang generasi millennial global yang warna-warni. Tugasmu bukan untuk menyamar jadi benang sutra Jawa asli. Tugasmu adalah menemukan caramu untuk memasukkan benangmu ke dalam anyaman ini, tanpa menghilangkan warna aslimu.”
Alika terdiam, memandangi hutan benang itu dengan perspektif baru. “Jadi… aku tidak harus memilih? Antara jadi ‘si gadis Jawa’ atau ‘si seniman Barat’?”
“Pilihan itu adalah ilusi, Sayang,” jawab Aisyah lembut. “Lihat aku. Apa aku penjaga tradisi seperti Mbak Rara? Tidak. Apa aku seniman kontemporer yang mengabaikan akar? Juga tidak. Aku adalah… perajut. Dan kau bisa menjadi apapun yang kau mau. Penari digital. Pelukis yang terinspirasi wayang. Sutradara film yang mengangkat cerita rakyat. Asal kau jujur pada benang yang kau bawa.”
Malam itu, Alika tidak bisa tidur. Dari kamar kecil di atas studio, ia bisa melihat cahaya lampu jalan menerangi instalasi benang di ruang bawah. Ia turun, dan duduk di lantai di bawah hujan benang itu. Ia mengambil buku sketsanya, dan mulai menggambar. Bukan sketsa untuk tugas atau proyek, tetapi coretan bebas. Ia menggambar dirinya sendiri sebagai sebuah bola benang kusut dengan banyak ujung. Lalu ia menggambar tangan-tangan—tangan dengan warna kulit berbeda, dari usia berbeda—masing-masing memegang sebuah ujung benang dan mulai mengurai, perlahan-lahan, bukan untuk meluruskannya, tetapi untuk menemukan pola di dalam kekusutannya.
Esok harinya, ia menunjukkan gambar itu pada Aisyah. “Ini… benang yang kubawa, Tante. Masih kusut. Tapi aku mulai ingin mengurainya. Bukan untuk meluruskannya, tapi untuk melihat polanya.”
Air mata kebahagiaan membasahi mata Aisyah. Inilah sambungannya. Inilah warisan yang bernapas. Bukan menyalin, tetapi memahami dan mentransformasi.
“Kalau begitu,” kata Aisyah sambil membuka laci, mengeluarkan seutas benang baru. Benang ini unik, campuran dari serat katun organik dan sedikit benang glitter sintetis, mencerminkan dunia Alika. “Ini untukmu. Ikatkan ke salah satu benang di sana, dan tuliskan cerita pertamamu di gulungan itu.”
Dengan tangan sedikit gemetar, Alika mengambil benang itu. Ia memilih untuk mengikatkannya pada sebuah benang berwarna tanah yang berasal dari cerita seorang petani perempuan—sebuah pilihan yang mengejutkan bahkan bagi dirinya sendiri. Di gulungan kertas kecil, ia menulis: “Benang pertama Alika. Kusut, berkilau, mencari pola. Diikat pada kekuatan yang sederhana dan tahan lama.”
Saat gulungan itu digantungkan, bergabung dengan ribuan suara lainnya, Aisyah merasakan sebuah kepenuhan yang dalam. Mbak Rara mungkin telah tiada, tetapi nadanya terus bergema dalam simfoni ini. Suaranya ada dalam benang-benang tradisi. Suara Aisyah ada dalam benang-benang yang menjembatani. Dan kini, suara baru Alika, dengan kekusutan dan kilaunya, telah bergabung.
Inilah warisan yang sesungguhnya. Bukan sebuah benda mati di dalam museum, tetapi sebuah proses hidup yang terus menyambung. Sebuah permadani raksasa yang terus ditenun, di mana setiap generasi menambahkan pola, warna, dan teksturnya sendiri.
Beberapa bulan kemudian, dalam sebuah pameran kelompok bertajuk “Generasi”, Alika memamerkan karya pertamanya: sebuah instalasi video dan benang. Dalam video, terlihat tangannya sendiri (dengan kutikula yang tidak rapi, cat kuku yang sudah terkelupas) sedang dengan sabar mengurai sebola benang yang sangat kusut. Suara latarnya adalah rekaman percakapannya dengan neneknya di Belanda (berbahasa Belanda campur Jawa), dan dengan Aisyah (dalam bahasa Indonesia). Di atas video, ia menggantungkan benang-benang yang telah diurai, tidak dalam garis lurus, tetapi dalam bentuk gelombang dan simpul yang sengaja dibuat, membentuk peta denah imajiner kota Yogyakarta dan Amsterdam yang tumpang tindih.
Judulnya: “Peta dari Kusut: Journey #1.”
Orang-orang berhenti, memperhatikan, bertanya-tanya. Seorang kritikus seni senior berbisik pada Aisyah, “Dia mirip gayamu dulu, tapi… lebih bebas.”
Aisyah tersenyum bangga. “Dia bukan mirip siapa-siapa. Dia adalah Alika. Itu lebih baik.”
Di akhir pameran, saat Alika berdiri di depan karyanya dengan wajah cerah dan percaya diri, Aisyah mendekat dan memberikan sebuah bungkusan kecil.
“Ini untuk perjalanan selanjutnya,” katanya.
Di dalamnya, Alika menemukan sebuah tusuk konde modern—desain sederhana dari baja tahan karat, dengan ujung berbentuk geometris yang abstrak. Bersama dengan catatan dari Aisyah: “Untuk menata kekusutanmu, atau sekadar untuk mengingat bahwa kau memiliki alat. Gunakan sesuai bahasamu.”
Alika memegang tusuk konde itu, lalu menatap instalasi benang raksasa di studio Aisyah yang jauh lebih besar dan hidup daripada karyanya. Ia melihat garis sambungnya yang jelas: dari sanggul tradisional Mbak Rara, ke kerudung hibrida Aisyah, hingga tusuk konde abstraknya sendiri.
Ia tidak lagi merasa seperti penipu. Ia merasa seperti penerus. Bukan penerus suatu bentuk, tetapi penerus suatu semangat: semangat untuk terus merajut, mempertanyakan, dan menciptakan bahasa baru dari warisan yang bernapas.
Dan di suatu tempat, Aisyah yakin, Mbak Rara tersenyum. Karena garisnya tidak putus. Ia hanya telah bercabang, berkelok, dan kini, bersiap untuk menjelajah wilayah-wilayah baru yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Simfoni seribu benang itu terus mengalun, dengan lebih banyak suara, lebih banyak warna, dan sebuah irama yang terus berubah, selamanya hidup.
Bab 13: Simfoni yang Abadi
Lima belas tahun setelah kepergian Mbak Rara, warisannya telah menjadi legenda yang hidup, bukan dalam museum, tetapi dalam ritme kehidupan sehari-hari. Studio Aisyah, yang kini telah berevolusi menjadi “Rumah Anyam”—sebuah pusat komunitas seni, arsip lisan, dan ruang inkubasi bagi seniman muda—telah menjadi landmark tersendiri di Yogyakarta. Sebuah rumah joglo yang diperluas, di mana atapnya yang tinggi menaungi ribuan benang dari instalasi hidup yang terus tumbuh. Itu bukan lagi sekadar karya seni; itu adalah ruang suci sekaligus ruang publik, tempat orang datang untuk merenung, bercerita, dan menambahkan benang mereka sendiri.
Aisyah sendiri, di usianya yang hampir lima puluh, telah mencapai sebuah ketenangan yang mendalam. Uban mulai bercampur dengan rambut hitamnya, yang sering ia ikat dalam sanggul rendah yang longgar, dihiasi tusuk konde kayu cendana di satu sisi. Tusuk konde peraknya kini lebih sering dipajang di kotak kaca di samping Kemben Bertanda Tangan Mbak Rara, sebagai benda pusaka yang dikeramatkan. Di lehernya, syal sutra tetap menjadi tanda tangan—kadang dikenakan sebagai kerudung longgar, kadang hanya sebagai aksesori.
Suatu pagi, ia duduk di serambi Rumah Anyam, menikmati teh jahe dan melihat Alika—kini seorang seniman instalasi yang sudah mapan dan asisten kurator di Rumah Anyam—memandu sekelompok mahasiswa asing. Alika menjelaskan filosofi di balik setiap benang dengan semangat yang tak pernah pudar, rambut ikalnya yang sekarang lebih terawat dihias dengan tusuk konde baja pemberian Aisyah.
“Tante, ada paket untukmu,” kata seorang relawan muda, menyerahkan sebuah kotak persegi panjang yang dibungkus kertas kraft.
Pengirimnya adalah sebuah yayasan seni di Singapura. Saat dibuka, isinya membuat Aisyah tersentak.
Itu adalah sebuah katalog pameran retrospeksi besar untuk seniman kontemporar Asia Tenggara. Di halaman judul, terdapat foto karya instalasi ikoniknya, “RAGAM: Dari Leher yang Sama”. Dan di sampingnya, dalam huruf yang lebih kecil tetapi sama pentingnya, terpampang foto karya Alika, “Peta dari Kusut: Journey #3”. Undangan resmi untuk kedua mereka, sebagai seniman multigenerasi yang mewakili Indonesia, tertempel rapi di dalamnya.
Ini adalah pengakuan tertinggi. Bukan untuknya sendiri, tetapi untuk kesinambungan itu. Untuk bukti bahwa konflik pribadinya, yang ia ubah menjadi seni, telah melahirkan sebuah bahasa yang mampu menyambung generasi dan bahkan diakui secara internasional.
Malam itu, di kediaman sederhananya di belakang Rumah Anyam, Aisyah tidak bisa tidur. Ia membuka lemari besi kecil di kamarnya, mengeluarkan dua benda: buku catatan kulit Mbak Rara yang sudah rapuh, dan buku sketsa pertamanya yang penuh dengan coretan panik tentang sanggul dan kerudung. Ia membuka keduanya secara bersamaan.
Di halaman pertama buku Mbak Rara: “Gerakan pertama bukanlah kaki. Ia adalah napas.”
Di halaman pertama buku sketsa lamanya: “Dinding yang Bernapas – konsep awal.”
Dua titik awal yang sangat berbeda, yang kini telah menyatu dalam aliran hidupnya. Ia mengambil pena dan buku catatan barunya—buku yang berisi ide-ide untuk memastikan Rumah Anyam tetap berkelanjutan setelah ia tiada.
Ia mulai menulis, bukan sebagai seniman yang panik, tetapi sebagai seorang penenun yang bijak:
“Warisan bukan untuk disimpan, tetapi untuk dihidupkan. Hidup berarti berubah, beradaptasi, bercabang.
Rumah Anyam harus tetap menjadi ruang yang aman bagi semua ‘kusut’. Di sini, setiap benang, seberantakan apapun, memiliki hak untuk dicari polanya.
Kepada Alika, dan kepada semua tangan muda yang akan datang: Jangan takut pada benang baru. Jangan juga terpaku hanya pada benang lama. Tugas kita adalah merawat proses anyamannya itu sendiri. Menjaga agar alat tenunnya tetap berfungsi, agar ceritanya terus diceritakan, agar setiap orang yang masuk merasa: ‘Benangku punya tempat di sini.’
Simfoni ini bukan milikku. Ia milik setiap perempuan yang pernah meninggalkan tanda di Kemben ini, di benang-benang ini, dan di hati mereka yang tersentuh. Aku hanya salah satu pemain musiknya. Sekarang, giliran kalian memegang alat musiknya.”
Ia menulis hingga subuh, merancang struktur kepemimpinan kolektif untuk Rumah Anyam, menetapkan dana abadi, dan menyusun rencana agar Kemben Bertanda Tangan dan instalasi benang bisa terus melakukan perjalanan, menjadi pameran keliling yang menginspirasi komunitas lain.
Pameran retrospeksi di Singapura menjadi momen puncak. Ruang galeri yang putih dan minimalis menjadi kontras yang sempurna untuk warna-warni dan tekstur dari karya Aisyah dan Alika yang dipamerkan berdampingan. Banyak pengunjung yang terpesona melihat garis yang menghubungkan sanggul tradisional dalam foto dokumentasi, mahkota anyaman raksasa, hingga peta digital dari benang kusut Alika. Itu adalah sebuah narasi visual tentang transformasi, ketahanan, dan regenerasi.
Dalam sebuah diskusi panel, seorang moderator bertanya pada Aisyah: “Apa yang ingin Anda wariskan kepada generasi berikutnya, selain karya fisik Anda?”
Aisyah tersenyum, memandang Alika yang duduk di sampingnya, lalu ke arah audiens.
“Saya tidak ingin mewariskan sebuah jawaban,” katanya, suaranya jernih dan tenang. “Karena jawaban saya adalah jawaban saya, untuk konteks dan pergulatan saya sendiri. Yang ingin saya wariskan adalah keberanian untuk bertanya, dan alat untuk merajut jawabannya sendiri.”
Ia berhenti sejenak, memastikan setiap kata tertangkap.
“Saya mewariskan sebuah keyakinan bahwa identitas bukanlah penjara dengan satu kunci. Ia adalah sebuah tenunan yang bisa selalu ditambahi benang baru. Bahwa tradisi dan keyakinan pribadi bukanlah musuh yang harus saling menghancurkan, tetapi bisa menjadi dua benang yang, jika dirajut dengan niat baik dan kesabaran, justru menciptakan pola yang lebih kuat dan lebih indah.”
Ia menunjuk ke arah slide yang memproyeksikan Kemben Bertanda Tangan. “Saya mewariskan bukti bahwa kita tidak sendirian. Bahwa setiap kita adalah bagian dari simfoni yang sangat panjang. Suara kita penting, tetapi ia menjadi bermakna ketika bergabung dengan suara yang lain—yang datang sebelum kita, dan yang akan datang setelah kita.”
Saat kata-katanya selesai, auditorium hening sejenak, lalu tepuk tangan meriah menggema. Banyak mata yang berkaca-kaca, terutama dari para perempuan muda yang mungkin sedang bergumul dengan konflik serupa.
Pulang ke Yogyakarta, Aisyah merasa sebuah siklus telah hampir sempurna. Ia telah menyampaikan pesan terakhirnya di panggung yang besar. Kini, waktunya untuk memastikan akarnya—Rumah Anyam—kuat dan siap untuk ditumbuhi tunas-tunas baru.
Suatu senja yang indah, beberapa tahun kemudian. Aisyah duduk di kursi goyang di serambi Rumah Anyam. Tubuhnya mulai merasa lelah yang berbeda, sebuah kelelahan yang damai. Di pangkuannya, terbaring buku catatan Mbak Rara dan buku sketsa lamanya, sudah ditutup. Alika duduk di tangga di bawahnya, kepala bersandar pada lututnya, mendengarkan.
“Alika,” panggil Aisyah lembut.
“Iya, Tante?”
“Rumah ini… sekarang adalah rumahmu. Benang-benang ini… sekarang adalah tanggung jawabmu untuk merawatnya, dan untuk mengundang lebih banyak tangan untuk merajut.”
Alika menoleh, matanya berlinang. “Aku… aku tidak tahu apakah aku bisa sekuat Tante.”
“Kau tidak harus kuat seperti aku. Kau harus jujur seperti dirimu. Itu yang lebih penting.” Aisyah mengulurkan tangan, memegang tangan Alika. “Ingat, Simfoni Seribu Benang tidak pernah tentang satu pemain solo. Ia tentang orkestra. Dan kau, Sayang, kini telah menjadi konduktornya.”
Matahari hampir tenggelam, menerangi Kemben Bertanda Tangan di dalam ruangan dengan cahaya keemasan. Ribuan benang yang tergantung memantulkan cahaya itu, menciptakan tarian cahaya dan bayangan di seluruh ruangan, seperti roh-roh para perempuan yang ceritanya tersimpan di sana sedang menari dengan riang.
Aisyah memejamkan mata, membiarkan kehangatan senja menyelimutinya. Dalam keheningan, ia bisa mendengar simfoni itu dengan sangat jelas: gemerisik benang Mbak Rara yang ditenun dengan disiplin, desahan napasnya sendiri saat merangkai kain di video, tawa cemas Alika saat pertama kali mengikat benangnya, dan suara-suara lain—ribuan suara—dari perempuan-perempuan yang telah menyentuh hidupnya dan hidup yang disentuhnya.
Ia melihat kembali perjalanan panjangnya. Gadis muda yang terpojok oleh sebuah undangan pernikahan. Perempuan yang memberontak dengan seni. Perajut yang menemukan bahasanya. Dan akhirnya, penjaga api yang meneruskan obor.
Tidak ada lagi kerudung versus sanggul. Keduanya telah larut, menjadi serat dalam tenun yang jauh lebih besar dan megah.
Dengan napas terakhir yang tenang dan senyuman tipis di bibir, Aisyah menyelesaikan simfoninya. Namun, orkestranya tidak berhenti. Di bawah pimpinannya yang bijak, di bawah tangan-tangan muda seperti Alika, musik itu terus mengalun. Benang-benang baru terus ditambahkan. Cerita-cerita baru terus ditenun.
Di Rumah Anyam, lampu-lampu dinyalakan. Suara diskusi, tawa, dan gesekan benang kembali memenuhi udara. Alika berdiri, memandang nenek angkatnya yang telah pergi dengan damai, lalu memandang ke dalam ruangan di mana seorang remaja putri dengan hijab warna-warni sedang dengan hati-hati mengikat benang barunya, dengan bimbingan seorang penari tua murid Mbak Rara.
Garisnya tidak putus.
Warisan itu bernapas.
Dan simfoni seribu benang, simfoni yang dimulai dengan sebuah kerudung di tengah geliat budaya sanggul, terus mengalun abadi.
[TAMAT]